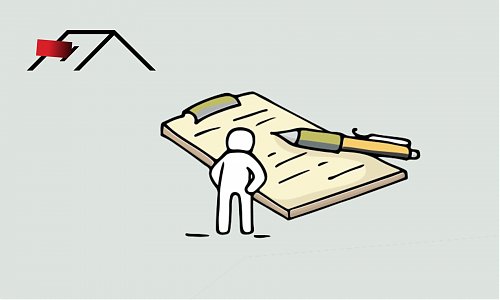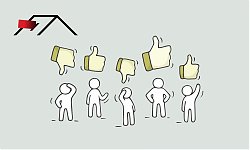25 tahun pasca-Reformasi, perjuangan keterwakilan politik perempuan masih sarat persoalan. Kendati konstitusi dan regulasi mengalami kemajuan. Namun peraturan teknis dan implementasi semakin menjauhi instrumen hukum dan pedoman.
Anggota KPU RI periode 2012-2017, Ida Budhiati mengingatkan ulang terkait pedoman penyelenggara pemilu adalah konstitusi. Pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara, baik dalam merespons, menjamin, maupun melindungi hak konstitusional warganya. Konstitusi bahkan jelas mengatur affirmative action keterwakilan politik perempuan sebagaimana Pasal 28H Ayat (2) perubahan UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
“Ini jadi satu kesadaran kolektif bahwa masyarakat Indonesia terutama perempuan itu mengalami diskriminasi, ketertinggalan di bidang politik sehingga dibutuhkan alat bantu, perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan,” tegas Ida dalam Diskusi Publik bertajuk “25 Tahun Reformasi: Quo Vadis Keterwakilan Politik Perempuan?” (20/6).
Implementasi Pasal 28 H Ayat (2) itulah yang kemudian mendasari penggunaan zipper system sebagai upaya mendorong perempuan mengantongi nomor urut kecil. Namun praktiknya, pemberlakuan zipper system melenceng dari konstitusi. “Kepastian yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang sekarang menjadi samar-samar dan nyaris tak terdengar. Ini kemunduran dalam regulasi untuk pemilu tahun 2024,” jelas Ida.
Belum lagi, ujar Ida, cara menghitung 30% dengan pembulatan ke bawah yang malah berpotensi mengurangi jumlah calon perempuan. Kemunduran lainnya adalah cara menempatkan perempuan yang tidak lagi disimulasikan di dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Seturut dengan itu, elemen teknis dalam PKPU tentang sistem informasi pencalonan juga menyulitkan partai yang hendak menempatkan perempuan di nomor urut kecil. “Situasi ini tentu tidak memberikan satu kontribusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, representasi perempuan di lembaga legislatif,” katanya.
Dalam hal regulasi, anggota Bawaslu periode 2008-2012, Wahidah Suaib menjelaskan pascareformasi terdapat tiga regulasi terkait keterwakilan politik perempuan. Pertama, UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Ini merupakan undang-undang pertama yang mengatur keterwakilan perempuan pada komposisi kenggotaan KPU dan Bawaslu. Hanya saja belum mengatur tentang keterwakilan 30% pada komposisi keanggotaan tim seleksi penyelenggara pemilu. “Kita lihat di Pasal 12 maupun Pasal 87 yang mengatur tentang pengangkatan KPU dan Bawaslu belum diatur tentang keterwakilan perempuan dalam timsel,” terang Wahidah.
Regulasi kedua adalah UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 12 tentang tim seleksi KPU dan Pasal 86 tentang tim seleksi Bawaslu sudah pula mengakomodasi keterwakilan perempuan. “Di situ sudah tertulis Presiden membentuk keanggotaan timsel 11 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan, tapi belum ada kata 30%nya,” kata Wahidah. Kekurangan lainnya adalah regulasi tersebut baru mengatur pada tim seleksi tingkat pusat. Hal ini, lanjut Wahidah, menjadi pertimbangan KPU dan Bawaslu untuk menutupi celahnya melalui PKPU maupun Peraturan Bawaslu, mengatur tentang 30% keterwakilan perempuan pada komposisi tim seleksi.
Ketiga, kemajuan regulasi terlihat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam hal pengangkatan anggota KPU dan Bawaslu, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 118 menegaskan bahwa komposisi tim seleksi perlu memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedkit 30%. Kemajuan lainnya, kata Wahidah, adalah regulasi teknis Bawaslu mengacu pasal afirmasi peningkatan keterwakilan perempuan.
“Dalam tahapan pendaftaran, dalam hal tidak tercapai 30% perempuan pendaftar maka diperpanjang pendaftaran selama 3 hari. Dalam hal tercapai, misalnya, jumlah pendaftar sudah sesuai dengan kebutuhan pendaftaran tapi belum tercapai 30% perempuan, maka diperpanjang pendaftaran khusus untuk perempuan.”
Wahidah menambahkan, pasal teknis lain memprioritaskan afirmasi untuk memasukkan perempuan apabila terdapat calon dalam jumlah sama.
Meski regulasi mendorong keterwakilan perempuan menguat, namun berkebalikan dengan implementasi. Kesenjangan komposisi anggota penyelenggara pemilu bahkan terlihat di tingkat pusat. Menurut Wahidah, komposisi keanggotaan 30% perempuan baik di KPU maupun Bawaslu hanya tercapai pada periode Bawaslu 2008-2012 dan periode KPU 2007-2012. “Setelah itu, memang hanya satu terus perempuan yang menjadi komisioner baik di KPU maupun di Bawaslu. Ini jelas sebuah kemunduran,” terang Wahidah.
Ketua Kaukus Perempuan Parlemen, Diah Pitaloka menyatakan hal penting yang bisa dilakukan adalah mengedepankan affirmative action sebagai sebuah narasi. Upaya penyelarasan ini bertujuan agar affirmative action terus menjadi pembicaraan dalam konteks demokrasi Indonesia.
“Jadi orang hari ini ngomong pemilu, ngomong capres, ngomong pileg, ya udah sifatnya sangat kompetitif, tapi nilai-nilai demokrasi seperti kita bicara emansipasi, kita bicara diskriminasi, kita bicara afirmasi, nilai-nilai demokrasi yang sifatnya substansi itu jarang lagi dibicarakan dalam pemilu,” ujar Diah.
Diah berpendapat narasi affirmative action perlu diwariskan kepada generasi baru. Sebab, generasi baru mempunyai nilai, perspektif, dan konsen isu beragam. “Nah kemudian bagaimana kita mentransformasikan narasi affirmative action, narasi emansipasi, dalam konteks politik hari ini,” kata Diah.
Pengembangan narasi affirmative action perlu diupayakan agar lintas generasi tak kehilangan makna. Bahkan secara praktik, ini menjadi langkah untuk tetap membangun strategi bersama terutama bagi perempuan Indonesia baik yang siap berkontestasi maupun untuk mendukung sesama perempuan di ranah politik.
Diah berpandangan membicarakan nilai-nilai demokrasi seperti membicarakan tentang strategi emansipasi merupakan jalan keluar dari jebakan demokrasi yang populis. Langkah ini menjadi cara untuk menepis sikap masyarakat yang bimbang bahkan apatis terhadap pemilu.
Maju mundurnya affirmative action keterwakilan politik perempuan, menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Hurriyah mudah dikenali. Yaitu, antara lain di parlemen, partai politik, dan lembaga penyelenggara pemilu.
Selain itu, capaian keterwakilan politik perempuan juga dapat diukur melalui kesenjangan jumlah perempuan di parlemen yang ada di tingkat nasional dan daerah. Meski pada skala ASEAN, capaian keterwakilan politik perempuan Indonesia di urutan 5 dari 11 negara anggota. Namun, situasi ini berbeda dengan angka keterwakilan politik perempuan di tingkat daerah.
“Di DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara ASEAN. Indonesia masih berada di bawah Kamboja bahkan jauh di bawah Laos. Jumlah keterwakilan politik di DPRD di Indonesia itu angkanya sekitar 16% di tahun 2021. Bandingkan dengan Laos yang angkanya mencapai 32%. Bandingkan juga misalnya dengan Vietnam yang angkanya 29%,” terang Hurriyah.
Padahal, imbuh Hurriyah, Kamboja, Laos, dan Vietnam belum menjadi negara demokrasi. Hal ini berarti kemajuan keterwakilan politik perempuan Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi elektoral bukanlah masih terbilang biasa. “Bahkan bisa dibilang jauh lebih slow dibandingkan misalnya rekan kita di Filipina dan juga di Thailand,” katanya.
Hurriyah menambahkan faktor kebijakan kuota berperan penting dalam mendorong keterwakilan politik perempuan di negara-negara ASEAN. Vietnam, misalnya, negara yang masih menganut pemerintahan otokrasi (sistem satu partai) mempunyai angka keterwakilan politik perempuan di DPR mencapai 30% dan 29% di tingkat lokal. Sedangkan di Indonesia, hal ini masih sebatas mimpi yang belum tercapai.
“Ada persoalan di mana implementasi kebijakan kuota itu masih sangat sarat dengan kepentingan politik partai. Bagaimana partai politik misalnya memperlakukan kebijakan kuota semata-mata sebagai persyaratan administratif untuk mengikuti pemilu. Bagaimana di lembaga penyelenggara pemilu misalnya semangat implementasi kebijakan kuota juga hanya dianggap sebagai sesuatu yang sifatnya himbauan moral bukan komitmen terhadap konstitusi kita,” tegas Hurriyah. []