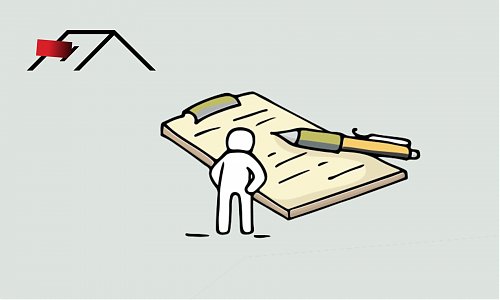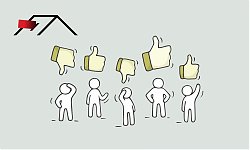Selasa (29/3), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem dengan dukungan dari program Asia-Pacific Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT), menyelenggarakan sebuah diskusi bertopik “APJED Goes to Public, Transitional Justice in Southeast Asia: Theory and Practice [APJED Goes to Public: Keadilan Transisional di Asia Tenggara: Teori dan Praktik]”. Diskusi ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada penulis Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy (APJED), jurnal yang dikelola oleh Perludem bersama Djokosoetono Research Center.
“Forum ini untuk berbagi gagasan penulis, memperluas audiens, meningkatkan trafik, dan sitasi,” kata Ketua Partai RESPECT, Theresia Joice Damayanti.
Aulia Nastiti, Ph.D kandidat Ilmu Politik, Universitas Northwestern adalah narasumber dalam diskusi ini. Ia menulis sebuah makalah “Transitional Justice in Southeast Asia: Theory and Practice [Keadilan Transisional di Asia Tenggara: Teori dan Praktik]”.
Dua Teori Utama Keadilan Transisional
Untuk menjelaskan keadilan transisional, Aulia menggunakan dua teori, yaitu teori keseimbangan kekuasaan oleh Sam Huntington, dan justice cascade (kaskade keadilan) yang banyak dikembangkan oleh Kathryn Sikkink.
Berbagai tindakan keadilan transisional tergantung pada mode transisi. Huntington mengidentifikasi tiga jenis transisi. Yang pertama adalah transformasi, di mana keputusan untuk melakukan reformasi berasal dari rezim lama yang kontra oposisi, dan mereka ingin mempertahankan kekuasaannya dengan mengubah iklim politik.
“Jadi, institusi boleh saja berubah, tapi kekuatan dominan tetap sama,” kata Aulia.
Kedua, transplacement. Elit lama menolak kekuasaan tetapi menegosiasikan pengaturan jalan keluar untuk menghindari langkah-langkah peradilan untuk membuat mereka bertanggung jawab. Ketiga, penggantian. Rezim atau elit lama kehilangan kekuasaan dan benar-benar digulingkan. Rezim baru sangat kuat.
Ketiga varietas tersebut menyebabkan hasil proses peradilan yang bervariasi. Pada tipe transformasi, proses keadilan mengarah pada impunitas. Dalam transplacement, akan ada keadilan yang dinegosiasikan. Dan dalam penggantian, mengarah ke pengadilan dan impunitas.
Sementara itu, dalam teori justice cascade (kaskade keadilan), dalam pengamatan Kathryn, mulai dari tahun 90-an, di antara banyak negara demokratisasi, ada peningkatan upaya untuk mengadakan pengadilan dan penuntutan hak asasi manusia untuk rezim pasca-otoriter. Fenomena ini disebut kaskade keadilan. Menurut definisi, teori kaskade keadilan adalah peningkatan global norma-norma akuntabilitas terhadap pelanggar hak asasi manusia, bahkan dengan cara demokratisasi yang beragam. Kaskade keadilan terutama didorong oleh penyebaran norma-norma internasional tentang perlindungan hak asasi manusia, oleh para aktivis hak asasi manusia, pengacara kepentingan publik, ahli hukum sebagai “pengusaha norma” yang selama beberapa dekade menghadapi tantangan hukum untuk mendorong perubahan.
“Jadi, dia sebenarnya mencoba menentang teori Huntington dengan mengatakan bahwa itu tidak terlalu tergantung pada mode transisi, karena kami melihat peningkatan upaya akuntabilitas, bahkan di negara-negara dengan mode transisi demokratisasi yang beragam. Teori ini sangat menekankan pentingnya faktor sisi permintaan, peran masyarakat sipil untuk menjelaskan munculnya penuntutan hak asasi manusia. Ini menjelaskan keadilan dari bawah, bukan kisah Huntington tentang perjuangan antar sekutu politik,” jelas Aulia.
Realitas Empiris di Asia Tenggara
Asia Tenggara, menurut Aulia, mengadopsi keadilan transisional dengan cara yang relatif tertunda daripada Amerika Latin atau Eropa Timur. Ada empat negara yang dianalisisnya, yakni Kamboja, Filipina, Indonesia, dan Timor Leste. Negara-negara ini mengadopsi beberapa langkah keadilan, tetapi tidak semuanya mengadopsi langkah-langkah tersebut secara sama.
Di negara-negara ini, Aulia mengidentifikasi tiga langkah paling umum dari keadilan transisional, yaitu komisi kebenaran, penuntutan pelaku atau pengadilan, dan beberapa upaya persiapan korban.
“Dalam kasus saya yang saya lihat, ketiga tindakan itu sebenarnya muncul di Kamboja, tetapi ketiganya sama-sama muncul di tiga kasus lainnya,” pungkas Aulia.
Kamboja
Keadilan transisional di Kamboja telah diadopsi secara khusus untuk menangani maskulinitas dan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah dari tahun 1975 hingga 1979. Ukuran keadilan utama di Kamboja adalah pembentukan Kamar Luar Biasa di Pengadilan Kamboja (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia/ECCC).
“Intinya bersifat hibrida karena yurisdiksi yang diterapkan di pengadilan ini adalah hukum internasional dan nasional. Sebagian pengadilan internasional dan sebagian pengadilan nasional untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan dan pelanggaran serius terhadap hukum pidana Kamboja, dan hukum humaniter internasional yang diakui oleh Kamboja,” katanya.
Keadilan transisional di Kamboja adalah proses yang relatif berhasil karena tidak hanya dapat menghukum orang-orang berpangkat tinggi di rezim Khmer Merah, tetapi juga berupaya untuk mendukung korban, produk budaya hukum yang berakar pada hukum internasional, dan memberi orang sarana untuk mulai mengenali, dan transisi dari dasar Khmer merah melalui pembentukan komisi kebenaran.
Dari penilaian teoritis, hasil keadilan transisional di Kamboja tidak dapat dilihat berdasarkan teori keseimbangan kekuasaan, karena teori tersebut tidak dapat menjelaskan penundaan waktu proses peradilan. Di Kamboja, proses keadilan transisional dimulai sangat terlambat, dan para penguasa baru negara Kamboja tidak diberi insentif untuk menghukum Khmer Merah bahkan setelah penggantian mereka.
“Jadi, modenya adalah penggantian. Huntington berhipotesis bahwa penggantian berarti bahwa hasilnya adalah hukuman. Memang benar, tetapi insentif sebenarnya lebih baik dijelaskan oleh teori kaskade keadilan. Ini sebenarnya datang dari tekanan internasional, norma-norma internasional tentang perlindungan hak asasi manusia. Namun, teori kaskade keadilan sedikit salah menempatkan aktor utama, karena peran masyarakat sipil di sini cukup minim, dibandingkan dengan lembaga internasional, dan tuntutan baru muncul setelah ECCC dibentuk oleh lembaga internasional,” ungkapnya.
Timor Timur (Timor Leste)
Keadilan transisional di Timor Leste terjadi dalam konteks negara-negara pascakolonial melawan bekas penjajah. Upaya untuk melakukan keadilan transisional muncul segera setelah Referendum 1999. Pemerintahan Transisi PBB membentuk unit kejahatan berat dan membuat pengadilan khusus yang diberi mandat untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus kejahatan perang terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh penjajah.
Namun keadilan transisional tidak terlalu berhasil mengadili mereka. Sebagian besar, prosesnya lebih menekankan pada pendekatan persiapan korban yang rekonsiliasi dan reparatif daripada mekanisme peradilan. Selanjutnya, langkah-langkah rekonsiliasi dan reparatif dibentuk melalui CAVR dan CTF, komite yang dibentuk bersama oleh Indonesia dan Timor Leste. Bahkan, para elite politik Timor Leste itu menggunakan wacana keadilan transisional secara selektif untuk mendukung agenda mereka sendiri.
“Karena kesadaran akan kendala geopolitik dalam menghadapi Indonesia, para pemimpin Timor Leste telah mempromosikan agenda rekonsiliasi sebagai pengampunan dan pelupaan. Karena itulah pemerintah Timor Leste memutuskan untuk lebih mengejar keadilan lebih pada tingkat terkait dengan membentuk komisi kebenaran dan pemulihan korban daripada berusaha memburu pelanggar HAM tingkat tinggi yang sebagian besar warga negara Indonesia,” jelas Aulia.
Dari penilaian teoritis, sudut pandang teori keseimbangan kekuasaan, keadilan adalah hasil antara penguasa yang keluar dan elit politik yang masuk, tetapi hasilnya tidak seperti yang dihipotesiskan oleh Huntington. Penggantian, tetapi langkah-langkah keadilan lebih dinegosiasikan.
Pada teori kaskade keadilan, teori ini lebih membantu dalam hal memahami bagaimana proses peradilan sebagian besar didorong oleh norma-norma internasional hak asasi manusia, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kekuatan permintaan tidak menghasilkan keadilan yang lebih komprehensif, seperti kasus Kamboja.
Filipina
Keadilan transisi di Filipina sehubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia Marcos terhenti, karena Marcos tidak dihukum meskipun diasingkan. Pemerintah pasca-Marcos mencoba untuk melakukan langkah-langkah keadilan transisional dengan membentuk komisi hak asasi manusia, namun kekuatan komisi ini sangat terbatas untuk membuat rekomendasi dan tidak memutuskan penuntutan. Keputusan ada di pemerintah.
“Studi mengatakan bahwa keadilan transisional pasca-Marcos dangkal dan performatif. Karena meskipun komite-komite itu telah dibentuk, tidak mencapai jawaban yang konklusif. Itu tidak memberikan penyelesaian kepada masyarakat, atau memberikan pada korban tindakan reparatif apa pun,” jelasnya.
Dari penilaian teoretis, Huntington mencirikan Filipina sebagai transisi penggantian, tetapi hasilnya kontras dengan harapan teoretis Huntington. Outputnya harus komprehensif dan mengarah pada hukuman rezim otoriter yang akan keluar.
Teori kaskade keadilan transisional juga memiliki kekuatan penjelas yang terbatas untuk memahami kasus Filipina. Tuntutannya sangat kuat, aktivisme masyarakat sipil cukup bersemangat, tetapi masih belum diterjemahkan ke dalam penerapan langkah-langkah keadilan yang berarti.
Indonesia
Indonesia memiliki berbagai kasus pelanggaran HAM: pembunuhan massal 1965, Tanjung Priok 1984, Timor Timur 1991, Reformasi 1998, dan Aceh 2003. Dalam semua kasus ini, hasilnya bervariasi, tetapi sebagian besar gagal memberikan langkah-langkah keadilan. Dalam beberapa kasus, keadilan dinegosiasikan, seperti di Aceh dan Timor Timur. Secara umum, keadilan didefinisikan dalam konsepsi alternatif dan terlokalisasi yang menguntungkan elit politik atau pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Bahkan upaya rekonsiliasi dan restoratif sangat terbatas.
“Hal yang paling mengecewakan terlihat dari cara pemerintah Indonesia menghadapi kekerasan antikomunis 1965 yang sampai saat ini masih ada aktivisme akar rumput dan tekanan internasional, di tingkat nasional negara masih memperlakukan komunisme sebagai ancaman laten. Jadi, bukan malah berusaha memberikan komisi kebenaran atau kesamaan sejarah kepada masyarakat, apalagi persiapan korban dan pengadilan bagi pelaku,” papar Aulia.
Sama seperti Filipina, kasus Indonesia sebenarnya tidak sesuai dengan ekspektasi teoritis. Transisi ini sesuai dengan mode transplacement, tetapi hasil keadilan sebagian besar adalah impunitas bagi diktator masa lalu. Menurut teori keseimbangan kekuasaan, terbatas dalam memahami berbagai hasil keadilan yang selektif di bawah proses transisi yang sama.
Dari sudut pandang kaskade keadilan, tuntutan yang kuat dan norma-norma hak asasi manusia tidak diterjemahkan ke dalam proses keadilan yang berarti.
Jalur Alternatif
Dari kasus-kasus empiris, satu pemahaman umum adalah bahwa keputusan politik elit tampaknya menjadi mekanisme kunci atau penyebab langsung dalam mendapatkan keadilan transisional. Ini tampak jelas di hampir semua kasus.
“Pertanyaan yang tersisa kemudian kepada kita, dalam kondisi apa elit politik akan memiliki insentif untuk mengejar proses keadilan,” tanyanya.
Sebagai refleksi atas kasus dan dua teori dominan yang ada, Aulia mengajukan alternatif penjelasan yang potensial. Yang pertama adalah, bahwa hasil aktual dari keadilan mungkin bergantung pada apakah para elit dapat menghindari norma-norma internasional dan beralih ke gagasan lokal tentang apa yang dianggap sebagai keadilan untuk melayani kepentingan politik mereka. Kedua, tergantung pada apakah para elit dapat membingkai kekerasan sebagai sesuatu yang sah sampai sejauh mana legitimasi kekerasan dilembagakan dalam memori kolektif. Ketiga, tergantung pada seberapa banyak rezim yang berkuasa saat ini benar-benar terlibat dalam melakukan kekerasan, dan sejauh mana kekuasaan dan pengaruh politik mereka dikompromikan jika mereka memutuskan untuk mengejar keadilan transisional. []
*Diterjemahkan oleh Catherine Natalia