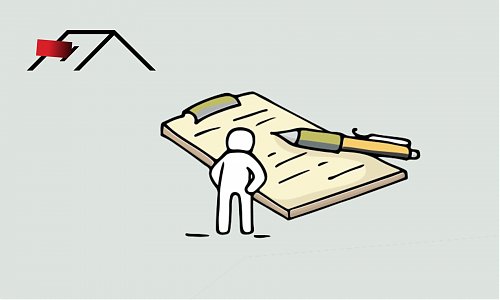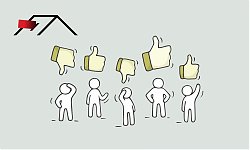Kekerasan politik terhadap perempuan meningkat di sebagian besar negara di dunia, dan terjadi di seluruh kawasan. Targetnya tak hanya kandidat atau politisi, tetapi juga pendukung, aktivis, pejabat pemerintah, bahkan pemilih. Sejak 2020, Meksiko, Kolombia, Cina, India, Brasil, Burundi, Myanmar, Afghanistan, Filipina, dan Kuba menjadi negara yang paling kejam terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Hasil studi Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 2016 menunjukkan, 81,8 persen perempuan anggota parlemen yang disurvei dari seluruh dunia pernah mengalami intimidasi psikologis, seperti kehadiran mereka tidak dianggap penting, pendapat mereka tidak dianggap serius, bahkan mereka tidak diberikan waktu bicara yang sama seperti laki-laki anggota parlemen. Di Filipina, senator Leila de Lima disebut sebagai orang tidak bermoral dan pezina oleh Presiden Rodrigo Duterte karena Leila mengkritik kepemimpinan Duterte.
Tengok pula Survei The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) tahun 2019 yang menunjukkan bahwa 2 persen dari pemilih perempuan pernah mendapatkan kekerasan fisik ketika mendaftar sebagai pemilih atau setelah memberikan suara. Salah satu kasus terjadi pada 14 Januari 2019, desa di Masisi, Kongo, diserang oleh kelompok militan Nduma Defense of Congo (Renové) dan Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo (APCLS) dengan tuduhan warga desa memilih calon yang salah. Pada serangan tersebut, dua orang perempuan menjadi korban pemerkosaan.
Kekerasan politik terus terjadi dan meningkat. Kejadiannya seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik.
Apa sebenarnya kekerasan terhadap perempuan dalam politik atau violence against women in politics?
United Nation dalam “Violence against women in politics” (2014) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam politik sebagai kekerasan yang terjadi di ranah politik, yang secara khusus menyasar perempuan. Kekerasan digunakan untuk memperkuat struktur tradisional, sosial, dan politik dengan menargetkan pemimpin perempuan yang menentang patriarki dan harapan serta norma sosial yang berlaku. Kekerasan ini membatasi mobilitas dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik, yang sangat mungkin mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis bagi politisi perempuan. Pemaksaan, juga perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dalam kehidupan publik atau pribadi politisi perempuan juga termasuk kategori kekerasan terhadap perempuan dalam politik.
Mona Lena Krook dan Juliana Restrepo Sanín dalam esai hasil studinya yang berjudul “Violence Against Women in Politics. A Defense of the Concept” (2016) memetakan konsep kekerasan terhadap perempuan dalam politik pada motif di balik kekerasan yang terjadi. Pertanyaan verifikasinya adalah: apakah kekerasan tersebut bertujuan untuk mengirim pesan kepada perempuan¾juga kepada masyarakat¾bahwa perempuan sebagai kelompok masyarakat tidak boleh berpartisipasi dalam politik.
Penjelasan tersebut jika disederhanakan, menjadi kekerasan politik terhadap perempuan jika perempuan politisi mengalami kekerasan karena mereka adalah perempuan. Karena menargetkan perempuan, maka akibatnya perempuan menghadapi bahaya di ruang yang biasanya aman bagi laki-laki, seperti pertemuan politik, acara resmi, kantor, bahkan rumah mereka sendiri.
Krook dan Sanín mencontohkan, pembunuhan terhadap Benazir Bhutto pada Desember 2007 bukanlah kekerasan terhadap perempuan, melainkan kekerasan dalam politik yang melibatkan politisi perempuan. Benazir tidak dibunuh karena dia perempuan dan tidak layak memimpin Pakistan, tetapi karena adanya kepentingan politik. Masalah hak perempuan untuk melayani sebagai pemimpin nasional telah diselesaikan oleh para pemimpin agama sebelum pemilihan pertamanya pada 1988.
Contoh kekerasan terhadap perempuan dalam politik bisa dilihat dari kasus pembunuhan Juana Quispe, seorang anggota dewan lokal di Bolivia, pada tahun 2012. Juana bersikap kritis terhadap wali kota, tetapi karena Juana adalah seorang perempuan, ia mendapatkan perlakuan buruk. Juana diminta untuk mengundurkan diri oleh wali kota, para pendukung wali kota, dan banyak anggota dewan lokal. Ia bahkan dicegah untuk mengikuti rapat dewan dan diskors sebagai anggota dewan. Ketika Juana diangkat kembali setelah persidangan selama tujuh bulan, Juana tidak mendapatkan gaji dengan alasan tak menghadiri rapat dewan. Satu bulan kemudian, dia ditemukan terbunuh.
Apa yang dialami oleh Juana bukanlah kasus tunggal di Bolivia. Politisi perempuan Bolivia kerap mengalami kekerasan dalam politik. Tidak jarang perempuan anggota dewan diminta mundur di tengah masa jabatan dan memberikan kursinya kepada laki-laki kader partai.
Sedikit berbeda dengan United Nation dan Krook dan Sanin, ACLED mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dalam politik sebagai kekerasan politik yang menyasar khusus perempuan atau anak perempuan. Dalam penelitiannya, ACLED melacak kekerasan politik yang menargetkan perempuan dalam politik (misalnya kandidat, politisi, pendukung partai politik, pemilih), dan perempuan lainnya dari semua lapisan masyarakat, terlepas dari pekerjaan atau keterlibatan langsung mereka dalam politik. Kekerasan politik yang dimaksud ACLED termasuk ancaman bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti mencalonkan atau memegang jabatan, mendukung atau memilih kandidat politik, memimpin kampanye hak asasi manusia atau inisiatif masyarakat sipil, dan sebagainya.
Konsep kekerasan politik terhadap perempuan memang terbilang baru, namun fenomena kekerasan terhadap perempuan yang melakukan kegiatan politik telah ada sejak lama. Pada 1950-an, misalnya, seorang perempuan anggota kongres dari Minnesota, mengedarkan surat dari suaminya kepada wartawan, yang menyatakan bahwa suaminya “muak dan lelah karena [dia] berkeliaran dengan pria lain sepanjang waktu” dan mendesaknya untuk pulang. Surat itu berdampak buruk pada kampanye pemilihannya kembali, sehingga ia tidak terpilih lagi. Citra perempuan anggota kongres tersebut rusak dengan cap “bukan perempuan baik-baik yang menelantarkan suaminya”. Perempuan yang memilih terjun ke dunia politik dan meninggalkan suami tidak disukai masyarakat.
Menarik sejarah lebih lampau lagi, kekerasan terjadi terhadap perempuan yang memperjuangkan hak pilih bagi perempuan. Perempuan aktivis digunjing tetangganya, diserang oleh massa yang marah, dipenjara, dipecat dari pekerjaan, dipisahkan dari anak-anaknya, bahkan dicerai suaminya. Film Suffragette (2015) menampilkan betapa masif kekerasan terhadap para perempuan aktivis.
Di dunia saat ini, kekerasan politik terhadap perempuan cenderung meningkat jelang pemilu, terutama apabila terdapat perempuan yang mencalonkan diri di tengah polarisasi yang kuat. Pengalaman Indonesia pada Pemilu 2019, sebagaimana hasil studi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) "Gangguan terhadap Hak Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan" (2021), perempuan calon anggota legislatif sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menjadi korban serangan disinformasi dengan narasi ujaran kebencian berbau misoginis.
Di tahun 2022, sejumlah negara di Asia menyelenggarakan pemilu di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum usai. Di Filipina, pemilihan presiden, pemilihan senat, dan pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Mei. Kemudian, Korea Selatan menyelenggarakan pemilu presiden pada 9 Maret. Kamboja ada pemilihan anggota dewan komune pada 5 Juni. Selain itu, Jepang pun menyelenggarakan pemilihan anggota majelis tinggi, paling lambat 25 Juli.
Serangan terhadap perempuan dalam pemilu yang terus dibiarkan akan melemahkan kredibilitas perempuan sebagai pengambil keputusan, dan pada waktu yang lain, akan membungkam suara dan keterlibatan perempuan di ruang publik, serta kian menjauhkan perempuan dari politik. []
AMALIA SALABI