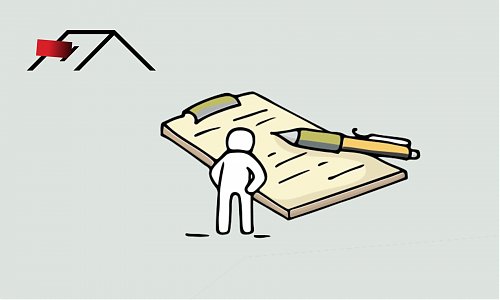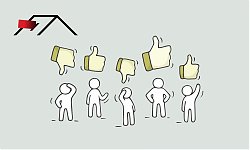Gilda R. Daniels dalam Voter Deception (2010) mendefinisikan voter suppression atau penindasan terhadap pemilih sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalangi pemilih atau kelompok pemilih tertentu yang tidak diinginkan agar tidak menggunakan hak pilih. Upaya ini bertujuan untuk beragam hal, termasuk memenangkan kandidat tertentu dengan mencegah pemilih yang teridentifikasi atau diperkirakan memilih kandidat lawan, untuk terdaftar sebagai pemilih atau menggunakan hak pilih.
Voter suppression merupakan fenomena yang lazim ditemukan di Amerika Serikat. Ada banyak contoh voter suppression dalam perjalanan demokrasi negara ini, mulai dari persyaratan untuk terdaftar sebagai pemilih yang diperketat, hingga pada bentuk voter suppression baru yang menggunakan teknologi untuk melakukan rekayasa perilaku pemilih atau hoaks yang disebarkan untuk menipu pemilih sehingga pemilih enggan memberikan suaranya.
Pada masa ketika budak yang baru dibebaskan diberikan hak pilih, negara-negara bagian Selatan memberlakukan berbagai syarat untuk bisa memilih, seperti pajak pemungutan suara dan tes melek huruf. Bahkan di tahun 2006, di beberapa kabupaten di negara bagian Virginia dengan populasi minoritas yang cukup besar, pemilih menerima panggilan otomatis yang memberikan informasi palsu bahwa mereka (kelompok minoritas) akan ditangkap jika mencoba memberikan suara pada hari pemilihan. Bahkan, disebarkan pula kabar bohong bahwa lokasi TPS telah berubah. Memang, fenomena khas pemilihan di AS, banyak selebaran berisi informasi yang salah yang disebarluaskan atas nama badan resmi pemerintah (Daniels 2010, hlm.348).
Brian Freeman dkk (2009, hlm.2-5) mengklasifikasikan tindakan voter suppression ke dalam empat kategori perilaku, yakni ancaman atau intimidasi langsung, disinformasi, mengganggu jalur komunikasi lawan sehingga lawan sulit berkomunikasi dengan pemilih, dan menantang hak seseorang untuk memilih, seperti hak pilih untuk disabilitas mental. Dari empat klasifikasi, intimidasi dan disinformasi merupakan bentuk voter suppression yang dampaknya sulit diukur.
Sementara itu, Transformative Justice Coalition Amerika Serikat menyebutkan ada 61 bentuk voter suppression. 35 bentuk voter suppression diantaranya saya kelompokkan berdasarkan tiga tahapan pemilu, yakni proses pendaftaran pemilih, kampanye, dan pemungutan-penghitungan suara.
| Pendaftaran Pemilih | Kampanye | Pemungutan-Penghitungan Suara |
|---|---|---|
|
|
|
Dari klasifikasi voter suppression yang dilakukan oleh Freeman dkk, juga bentuk-bentuk voter suppression yang disebutkan oleh Transformative Justice Coalition, dapat disimpulkan bahwa voter suppression dapat dilakukan oleh dua aktor. Pertama, kandidat, tim kampanye kandidat, dan pendukung kandidat. Kedua, pembuat kebijakan melalui peraturan di undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
Aturan-aturan voter suppression di UU Pemilu
Penulis mengidentifikasi sedikitnya ada dua aturan di dalam Undang-Undang Pemilu No.7/2017 yang membuka celah terjadinya voter suppression, yakni syarat untuk memberikan hak pilih dan layanan pemungutan suara.
Pertama, isu syarat memilih. Pada bagian hak memilih di UU, disebutkan bahwa semua warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun berhak memilih. Namun, Pasal 348 membatasi hak memilih itu dengan mengatur bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah yang dapat menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Tanpa menunjukkan KTP elektronik, seseorang yang sebetulnya telah memiliki hak pilih tak dapat memberikan suaranya.
Hal itu terjadi juga pada UU Pilkada No.10/2016. Pasal 57 menghendaki agar KTP elektronik menjadi penentu bisa tidaknya hak pilih digunakan.
Sedikit kelonggaran terjadi berkat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XVII/2019 yang menyebutkan bahwa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) masih dapat dipergunakan hingga perekaman KTP el telah mencapai 100 persen. Putusan itulah yang mencegah terjadinya voter suppression secara meluas pada Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serental 2020 sebab masih ada pemilih yang belum memiliki KTP el.
Single number identity yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil memang digunakan di beberapa negara untuk mendata pemilih, seperti di Norwegia, Swedia, Albania, dan Spanyol (ACE Project). Tujuannya, untuk mengurangi biaya pendataan pemilih. Namun, baik pendataan berdasarkan nomor identitas nasional maupun penunjukan kartu fisiknya, pada praktiknya di berbagai negara termasuk Indonesia, kerap tak menguntungkan kelompok-kelompok marginal dan sangat bergantung pada penjangkauan layanan administrasi negara.
Di Indonesia, di setiap pemilihan, hak pilih masyarakat adat, disabilitas, pemilih di lapas dan transgender selalu menjadi isu. Masyarakat adat misalnya, tak bisa mengakses layanan kependudukan lantaran tinggal di tanah-tanah dan hutan adat yang tak diakui oleh Pemerintah sebagai wilayah administrasi.
Begitu pula dengan kelompok disabilitas mental yang pada Pemilu 2019 menjadi korban voter suppression secara terang-terangan. Para pihak di tengah sengitnya kompetisi Pilpres dua kandidat saling menantang hak pilih disabilitas mental. Tantangan itu berkelindan dengan hoaks yang beredar, yang menyebut KPU tengah memberikan hak pilih kepada orang gila.
Dalam hiruk pikuk pemenuhan hak pilih itu, saya tak pernah mendengar tentang hak pilih bagi tunawisma. Entah berapa jumlah tunawisma yang tak memiliki KTP elektronik di Indonesia dan tentu tak terjangkau oleh pencocokan dan penelitian (coklit) petugas lantaran tak memiliki rumah. Padahal, salah satu bentuk voter suppression ialah tak diakomodasinya hak pilih bagi tunawisma.
Di Pemilu 2019 pun, meski memiliki KTP elektronik namun tidak terdaftar di DPT, pemilih hanya bisa menggunakan hak suaranya di RT dan RW yang tertera di KTP el mereka, sebuah aturan yang juga dimuat di RUU Pemilu versi 26 November 2020. Hal ini tentu bisa diidentifikasi sebagai voter suppression bagi para pekerja yang mesti menjalankan dinas dadakan sebab Indonesia juga tak memiliki skema early voting atau pemilihan pendahuluan dan absentee voting atau memilih tanpa kehadiran.
Pembuktian kepemilikan KTP el atau dokumen kewarganegaraan dengan segala batasan-batasannya, seperti jika pemilih pindah memilih maka berdampak pada surat suara yang ia dapatkan, memang menjadi masalah dalam pemenuhan hak pilih di Indonesia. Hak pilih yang menjadi kepentingan individual pemilih diperhadapkan dengan kepentingan aktor peserta pemilu untuk mencegah kecurangan seperti memberikan suara berulang, dan kepentingan aktor negara dengan penertiban catatan kependudukan dan kewarganegaraan. Padahal, teknologi bisa diberdayakan untuk merekognisi pemilih tanpa kartu identitas, seperti melalui biometrik. Tentu dengan catatan data biometrik pemilih tak boleh diberikan kepada pihak mana pun kecuali KPU. Atau, adanya pengakuan terhadap identitas khusus masyarakat adat yang belum merekam catatan kependudukan, serta akomodasi khusus bagi pemilih di daerah konflik dan bencana alam.
Kedua, ketiadaan early voting dan berbagai pilihan layanan pemungutan suara. Pasca pelaksanaaan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi, muncul diskursus publik bahwa Indonesia memerlukan metode pemungutan suara lainnya selain memilih di TPS pada hari pemungutan suara. Early voting, absentee voting, bahkan internet voting atau i-voting diusulkan. Intinya, memperbanyak layanan pemungutan suara untuk pemilih agar pemilih dengan situasi khusus tetap dapat memberikan suaranya dengan aman.
Di Estonia, ada 10 metode pemungutan suara yang dapat dipilih oleh pemilih dengan ragam kondisi, diantaranya yakni memilih di TPS, memilih lewat telepon, memilih lewat pos, i-voting, dan memilih dari rumah. Estonia memanfaatkan kartu identitas nasional untuk mengidentifikasi pemilih dan menyambungkan basis data pemilih online dengan data pemilih yang telah memberikan suaranya.
Revisi UU Pemilu diperlukan
Revisi UU Pemilu yang berperspektif perlindungan dan perluasan layanan hak pilih diperlukan. Sebagai pemilih, kepentingan terhadap UU Pemilu ialah adanya regulasi yang menjamin bahwa hak suara bisa digunakan secara mudah dan aman, tersedianya berbagai macam layanan pemungutan suara yang dapat dipilih, peserta pemilu yang berkualitas dan berintegritas, serta penghargaan terhadap suara pemilih dengan hasil pemilu yang akurat, yang mencerminkan pilihan pemilih.
Bentuk-bentuk voter suppression sebagaimana yang disebutkan oleh Transformative Justice Coalition juga layak untuk mendapatkan perhatian para penyelenggara pemilu. Tak hanya mengakomodasi hak pilih kelompok rentan, namun juga melakukan sosialisasi yang masif terkait syarat menjadi pemilih dan segala hal tentang pemilu, dan memberikan bimbingan teknis yang memadai kepada petugas pemilihan agar tak ada ketidaktahuan yang berujung pada hilangnya hak pilih seseorang.
Dengan tren disinformasi dan disrupsi informasi di internet yang semakin meningkat, pemilih juga rentan termanipulasi oleh konten-konten di media sosial, juga iklan politik dengan penargetan pemilih berdasarkan kriteria tertentu. Ketersediaan informasi yang cukup mengenai pemilihan penting untuk ada di setiap media sosial penyelenggara pemilu. Begitu juga dengan pentingnya kerjasama antara penyelenggara pemilu dan platform media sosial dalam penanganan disinformasi dan intimidasi terhadap pemilih yang disebarkan di media sosial.
NURUL AMALIA SALABI
Peneliti Perludem