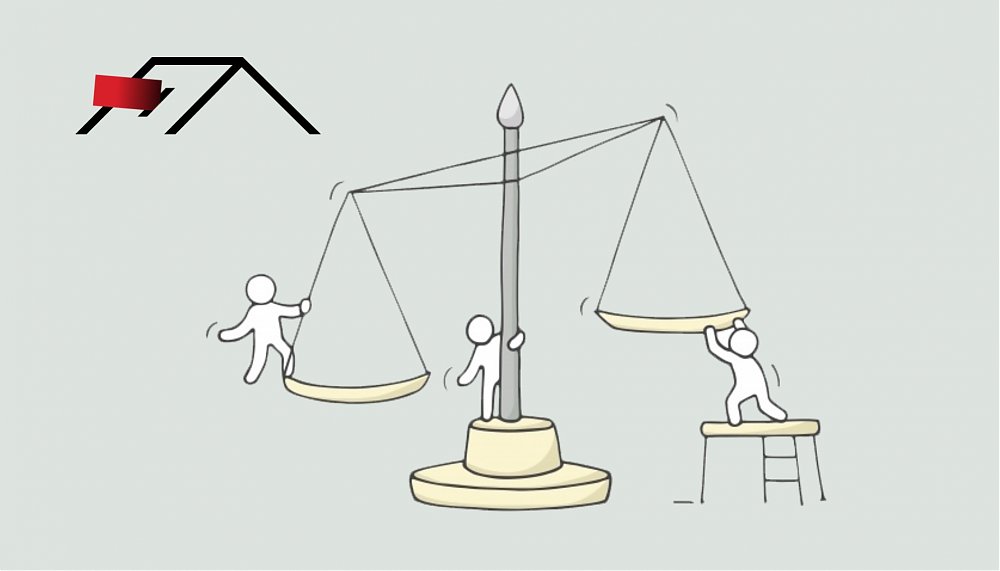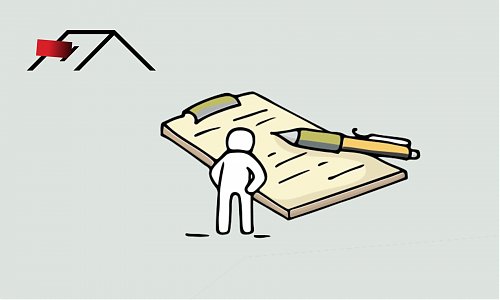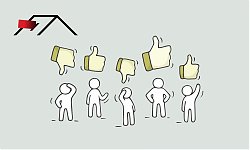Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan surat edaran yang berisi himbauan pada partai politik untuk mematuhi putusan MA. Sikap KPU ini semakin menguatkan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan mengenai syarat 30% pencalonan perempuan di tiap daerah pemilihan DPR/DPRD. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga peradilan etik pemilu harus meluruskan keadaan ini dengan mengeluarkan putusan sidang etik yang sejalan dengan putusan peradilan MA.
“Kan harusnya vonis dilawan dengan vonis. Sementara fatwa itu tidak mengikat, jadi nggak bisa vonis dilawan dengan fatwa,” kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar dalam diskusi “Jaga Kualitas Pemilu: KPU Patuh pada Putusan MA - DKPP Tegas Sanksi Penyelenggara” secara daring (6/10).
Zainal menilai putusan MA terkait keterwakilan 30 persen perempuan sudah benar secara materiil. Menurutnya, mau menggunakan pendekatan apapun keputusan MA sudah tepat, karena memang ada sesuatu yang ingin dicapai.
Zainal menganggap aneh logika KPU mengeluarkan surat edaran pada partai politik. Ia menerangkan, bahwa produk hukum yang dikeluarkan secara benar oleh lembaga yang memiliki kewenangan adalah sah dan mengikat. Keputusan MA sudah final karena tidak ada lembaga lain lagi untuk banding.
“Jadi memang haram ke bawah dan wajib ke atas. Affirmative action itu masuknya dalam konsep equity, kita nggak bisa pake filosofi equality before the law,” tegas Zainal.
PKPU harus direvisi karena diperintahkan secara hukum. PKPU dan Undang-Undang merupakan satu paket dalam menjalankan pemilu. Dengan mengeluarkan surat edaran itu, Zainal mengibaratkan, KPU memilih memukul menggunakan gabus, sementara sebenarnya mempunyai palu untuk memukul.
“KPU harus sadar bahwa ini adalah kepentingan politik, kalau membiarkan adanya lubang kosong seperti ini, sama halnya KPU sengaja membuat lubang api,” tegasnya.
Resikonya lanjut Zainal, jika aparatur negara tidak menjalankan putusan hukum maka hal itu masuk tindakan sewenang-wenang. Untuk itu DKPP sebagai dewan etik yang mengawasi KPU harus bertindak tegas, karena KPU tidak menjalankan putusan hukum, perintah pengadilan dan peraturan perundangan yang ditetapkan di pengadilan.
“DKPP mau tidak mau harus bertindak profesional. DKPP tidak boleh main-main, karena pertaruhannya adalah pemilu. Dan Ini persoalan masa depan pemilu,” sambungnya.
Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menjelaskan, demokrasi yang substantif tidak akan terjadi jika keterwakilan perempuan tak diwadahi. Hal itu akan berdampak pada kebijakan yang dihasilkan akan bias dan timpang.
Bivitri melihat PKPU 10/2023 terlalu matematis dan tidak memihak pada keterwakilan perempuan. Ia menyebut aturan itu hanya memihak pada partai politik yang gagal melakukan pendidikan politik dan membangun sistem integritas.
“Kegagalan itu bukannya diatasi, tapi malah ditutupi dengan merusak sistem pemilu kita. Yang buruk partainya yang dirusak pemilunya,” kata Bivitri.
Keterwakilan perempuan dalam partai politik selama ini masih artifisial karena tujuannya kekuasan, bukan demokrasi. Ia menyoroti fenomena umum di partai politik, yang hanya menempatkan kader perempuan untuk memenuhi kuantitas dan mengajak perempuan terkenal untuk pendulangan suara.
Lebih lanjut, Bivitri menilai upaya KPU untuk tidak melakukan revisi PKPU berdampak pada kelonggaran hukum yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh partai politik untuk kepentingannya. Hal itu juga akan membuat proses pemilu tidak substantif, karena tidak pernah ada suatu ketegasan.
Anggota KPU periode 2004-2007, Valina Singka Subekti menyayangkan tindakan KPU tersebut. Menurutnya keterwakilan perempuan minimal 30 persen sudah menjadi komitmen nasional untuk menghadirkan pemilu yang berintegritas. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mestinya KPU merevisi PKPU dan memastikan keterwakilan perempuan melalui regulasi yang jelas.
“Bukan dengan membuat nota dinas surat edaran pada partai, tapi KPU mestinya merevisi PKPU dan partai wajib melaksanakan PKPU yang dibuat,” terang Valina dalam diskusi bertajuk ‘Jaga Kualitas Pemilu: KPU Patuh pada Putusan MA- DKPP Tegas Sanksi Penyelenggara’ pada Jumat, 06 Oktober 2023.
Valina menyoroti masalah kemandirian KPU yang terus menurun. Menurutnya, kemandirian penyelenggara pemilu adalah bagian integral dari election with integrity yang harus tercermin dari kebijakan secara keseluruhan.
Lebih jauh, ia menjabarkan persoalan kemandirian KPU itu erat kaitannya dengan konstruksi awal pembentukan lembaga. Sejak awal KPU dikonstruksikan memang tidak sama dan setara dengan lembaga lain. Menurutnya, melalui istilah mandiri ada keinginan KPU tidak sepenuhnya independent, misalnya dengan aturan-aturan turunan yang semakin mengikat KPU seperti, sistem recruitment, pembuatan regulasi, dan anggaran pemilu.
“Ketiga hal itu membuat KPU tidak bisa hadir sepenuhnya menjadi lembaga yang independen. Karena itu penyelenggara pemilu harus diawasi. Dan itu bukan persoalan, karena sekarang sudah ditekan dan diawasi aja masih diterbas saja,” ungkapnya.
KPU Membuat Perjuangan Perempuan Mundur
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya, Dhia Al-Uyun menerangkan, maksud dari affirmative action adalah kebijakan yang digunakan untuk mengoreksi diskriminasi, karena sebelumnya memang ada diskriminasi terhadap perempuan. Hal itu diatur dalam konstitusi pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
Lebih jauh, Dhia menerangkan, sejak 24 Juli 1984 Pemerintah Indonesia resmi meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sebagai informasi, CEDAW lahir dari pengalaman diskriminasi perempuan di berbagai belahan dunia dan perjuangan panjang untuk membangun komitmen global bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia.
“Jadi kalau KPU bermain-main dengan regulasi keterwakilan perempuan, itu konteks ke atas akan banyak. Tidak lagi masalah UUD, tapi juga komitmen internasional. Dan itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan lagi,” terang Dhia.
Menurut Dhia, perjuangan perempuan untuk kesetaraan sudah berlangsung dan berkembang panjang sekali. Dengan tidak direvisinya PKPU tersebut, akan membuat perjuangan perempuan mundur kembali, kesetaraan yang diupayakan oleh pemerintah selama ini juga tidak akan terwujud.
“Kalo dibiarkan luka itu (diskriminasi perempuan) tidak akan tertutup sempurna,” tegasnya.
Untuk melaksanakan putusan MA, lanjut Dhia, tidak diperlukan ahli hukum lain, karena sudah jelas semua aturannya. Kecacatan dalam regulasi itu kalau tidak segera dibetulkan akan membawa pada hal buruk yang lebih banyak.
“Semoga KPU bisa berakal sehat untuk merubah PKPU, karena ini sangat penting sekali. Kalau dibiarkan akan membawa kesetaraan gender mundur lagi,” pungkas Dhia. []
AJID FUAD MUZAKI