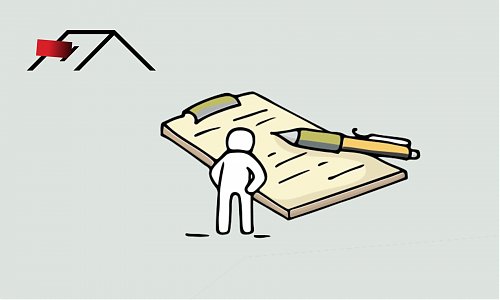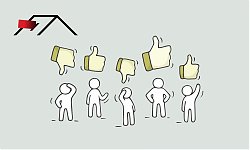Feminisme pemilu adalah paradigma kesetaraan berbasis gender dan antikekerasan dalam pemilu untuk menciptakan keadilan. Pemilu sebagai satu-satunya jalan mencapai kekuasaan demokrasi ternyata bisa tidak menjamin perempuan berpartisipasi. Menggunakan paradigma ini, kita bisa menyimpulkan bahwa demokrasi di suatu negara ternyata lebih banyak yang berarti “dari, oleh, dan untuk lelaki”.
Tawaran feminisme pemilu hadir karena ketika perspektif kepemiluan membahas perempuan, lebih banyak hanya berkutat pada jumlah dan kuota. Padahal, kehadiran dan keterwakilan perempuan dalam pemilu terkait ragam variabel dan konteks yang kompleks. Feminisme pemilu akan mencoba membongkar ketidakadilan politik gender dalam domain struktur hukum, implementasi, kultur, dan individu pada konteks pemilu (D’ignazio & Klein 2020). Semakin utuh pemahaman feminisme dan pemilu maka semakin baik kita bisa menjelaskan kualitas adil gender suatu negara.
Sebagai contoh, feminisme pemilu bisa digunakan untuk mempertanyakan posisi perempuan di suatu negara. Amerika Serikat misalnya, negara berstatus “full democracy” (The Economist) dan “free” (Freedom House) ini ternyata mengalami timpang gender di semua jabatan publik yang dipilih melalui pemilu tapi punya keadaan layanan negara yang lebih menjamin kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dibanding negara Rwanda yang punya keterwakilan perempuan di parlemen lebih dari 50%.
Ketika ada hierarki gender dalam hukum pemilu dan implementasinya, di situ ada ketidakadilan. Jika hukum pemilu dan implementasinya sudah menjamin tidak ada diskriminasi, ketidakadilan bisa tetap terjadi jika masih ada ketimpangan gender dalam kultur. Ketika partisipasi proses pemilu tidak representatif gender, ketika keterpilihan pejabat hasil pemilu timpang gender serta berkebijakan diskriminatif, maka ketidakadilan nyata terjadi.
Feminisme pemilu pun merupakan paradigma yang menyertakan konsep gelombang feminisme. Gelombang feminisme pertama merupakan perjuangan untuk membebaskan merempuan dari diskriminasi hak dalam hukum publik, salah satunya hak politik. Gelombang feminisme kedua secara radikal menempatkan patriarkisme sebagai sebab sistemik ketidakadilan sehingga, identitas tubuh perempuan harus mendapatkan afirmasi dalam struktur hukum negara dan kultur masyarakat. Gelombang feminisme ketiga secara interseksi menghubungkan identitas marjinal lainnya serta ragam isu untuk mencapai kesetaraan dan keadilan yang lebih luas/bermakna. Tiga gelombang ini menyertakan varian di dalamnya bukan sebuah pencapaian kesempurnaan melainkan pilihan pisau analisis yang ketajamannya terikat konteks.
Paradigma feminisme yang disandingkan konsep kepemiluan akan menganalisis derajat kesetaraan, kebebasan, dan keadilan gender dalam pemilu. Menyertakan keduanya akan lebih utuh merasakan ketidakadilan gender di suatu negara demokrasi. Sehingga, kita bisa mengetahui sebab dan solusi yang lebih tepat adanya ketidakadilan di partai politik, kepesertaan pemilu, kampanye, pemungutan suara, dan pemerintahan terpilih.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan standar pemilu demokratis. Standar utama berasal dari berbagai deklarasi dan konvensi internasional, regional, serta Deklarasi dan Konvensi PBB tentang HAM dan dokumen hukum lainnya. Sedangkan standar tambahan berasal dari laporan akhir pemantauan pemilu (internasional/domestik), evaluasi implementasi prinsip bebas adil suatu negara yang berdampak perbaikan undang-undang pemilu; dan model kode etik pemilu yang dikembangkan organisasi internasional, pemerintah, atau LSM.
Sejumlah paradigma keadilan amat mungkin dibutuhkan untuk memastikan standar kepemiluan dipenuhi, bukan sebatas formalitas prosedur. Paradigma HAM misalnya, dibutuhkan untuk memastikan keadilan HAM dalam pemilu sehingga bisa demokratis secara prosedural dan substansial. Amat mungkin paradigma HAM atau lainnya tidak bisa mendeteksi ketidakadilan berbasis gender dalam pemilu sehingga feminisme pemilu dibutuhkan.
Pilihan ketentuan dan sistem politik
Mari kita gunakan feminisme pemilu menilai keadilan pemilu Indonesia. Keterwakilan perempuan di parlemen pusat dan daerah masih di bawah 30%. Kepala daerah amat timpang gender. Indonesia memang pernah punya presiden perempuan tapi itu pun melalui pergantian wakil karena presiden lelaki dimakzulkan. Timpang gender keterpilihan jabatan politik itu semua menyerta suplai kepesertaan yang juga timpang gender.
Hasil analisis feminisme pemilu salah satunya mengusulkan afirmasi perempuan dalam undang-undang pemilu. Memberlakukan ketentuan penguatan posisi perempuan pada 4K: kepesertaan partai, kuota pencalonan, kepanitiaan seleksi penyelenggara pemilu, dan keanggotaan penyelenggara pemilu. Penekanannya, pelibatan perempuan minimal 30% di segala aspek partisipasi politik.
Jika ingin jadi peserta pemilu, partai politik harus punya kepengurusan dan pencalonan 30% perempuan. Jika ingin banyak perempuan jadi anggota penyelenggara pemilu, keanggotaan panitia seleksi pun harus ada perempuan untuk lebih mungkin memilih banyak perempuan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Meski ketentuan itu cukup dipenuhi, keterpilihan perempuan masih timpang gender. Analisis feminisme pemilu yang lebih dalam menemukan, biaya tinggi pesta demokrasi membuat perempuan sulit mengimbangi dominasi lelaki berkontestasi. Kampanye di ruang publik serta frekuensi publik (TV dan radio) yang tidak dikuasai negara membuat lelaki calon lebih dikenal pemilih. Akses ekonomi yang belum setara membuat lebih banyak perempuan yang minim modal kampanye. Pendana atau sponsor pun lebih percaya mendukung lelaki karena pertimbangan peluang terpilih.
Lebih dalam lagi, feminisme pemilu menyimpulkan bahwa sistem politik Indonesia pada dasarnya relatif tidak ramah perempuan. Sistem pemerintahan parlementer lebih ramah perempuan tapi Indonesia memilih sistem presidensial. Parlemen bersistem multipartai ekstrem membuat undang-undang yang menyetarakan warga sulit untuk disahkan. Sistem pemilu Indonesia memang proporsional yang memang lebih ramah perempuan dibanding sistem distrik, tapi varian daftar terbuka lebih menghambat perempuan terpilih dibanding varian tertutup karena kontestasi antarindividu kontradiktif dengan solidaritas perempuan.
Mengingat asal
Terakhir, feminisme pemilu pun penting untuk mengingatkan kita bahwa awal gerakan feminisme merupakan perjuangan hak politik di pemilu. Rosemarie Putnam Tong dalam “Feminist Thought” menjelaskan, setelah perjuangan pendahuluan hak kesetaraan pendidikan, perjuangan gerakan feminisme gelombang pertama (Abad ke-19) adalah hak memilih di pemilu. Ialah John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill yang menginspirasi bahwa, perempuan harus punya hak pilih agar setara dengan lelaki. Gerakan feminisme penting untuk biasa kembali ke gelombang pertama feminisme dalam menggunakan warna-warni spektrum analisisnya.
Hak politik itu tentu saja belum cukup diperjuangkan mengingat fakta ketidakadilan gender dalam kepesertaan, persaingan kampanye, keterpilihan, dan kebijakan. Tidak tepat jika feminisme menjauhi pemilu dengan alasan tidak ada lagi larangan perempuan berpolitik, baik hak memilih maupun dipilih.
Bagi pasangan Mill, pemilu bukan hanya bisa mengekspresikan pandangan politik personal perempuan tapi juga bisa mengubah sistem, struktur, dan sikap yang berkontribusi mengubah opresi diri dan orang lain. Perempuan memang punya hak memilih dan dipilih tapi ini belum cukup sebagai capaian perjuangan politik gerakan perempuan selama keterpilihan dan kebijakan pemerintahan hasil pemilu masih timpang dan tidak adil gender.
Gerakan perempuan Indonesia sebetulnya relatif banyak mencapai hal positif dibanding gerakan lainnya, khususnya pasca-Soeharto. Ketentuan afirmatif dalam konstitusi Indonesia, merupakan bagian dari capaian gerakan perempuan. Pasal 28H (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bertuliskan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan konstitusional ini yang kemudian melahirkan ketentuan afirmatif minimal 30% perempuan di undang-undang partai politik dan undang-undang kepemiluan. Bahkan ketentuan afirmatif itu pun digunakan kelompok marjinal lain untuk mencapai keadaan yang lebih bebas, setara, dan adil.
Setelah semua itu, amat disayangkan jika gerakan perempuan dengan feminismenya menjauhi pemilu. Belakangan, solidaritas keadilan melemah lalu yang menguat adalah kuantitas perempuan berdasar dinasti dan popularitas. Sehingga, Yakinlah bahwa “the personal is political” dan “one person, one vote, one value” selalu potensial bersenyawa untuk mencapai kesetaraan. Tak ada demokrasi tanpa pemilu, tak ada keadilan tanpa keterlibatan perempuan dalam demokrasi. []
USEP HASAN SADIKIN