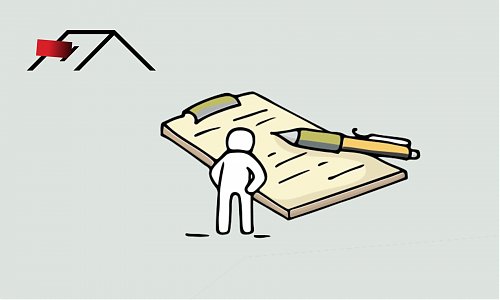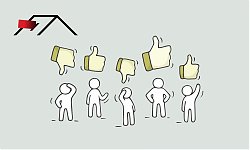Komisi Pemilihan Umum dinilai telah mengabaikan suara publik terkait pengaturan pencalonan 30% perempuan DPR/DPRD di setiap daerah pemilihan. Penilaian disampaikan oleh ahli dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Perkara No. 110-PKE-DKPP/IX/2023.
“Bahwa KPU paling tidak telah melanggar prinsip mandiri, jujur, adil, akuntabel, dan profesional. Sejak awal anggota KPU menyadari bahwa peraturan itu tidak kokoh dan bertentangan dengan suara publik,” ucap akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini dalam sidang di DKPP, Jakarta (22/9).
Terjadi perubahan atas Pasal 8 ayat (2) PKPU yang disepakati secara tertutup antara DPR dan KPU dan tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Titi menyesalkan, sikap KPU yang mengabaikan masukan publik dan hanya menampung suara fraksi-fraksi di DPR.
“Publik adalah aktor utama pemilu yang juga harus dilayani dengan baik, bukan hanya partai politik,” sambungnya.
Lebih jauh, Titi menjelaskan, siklus pemilu terbagi menjadi tiga periode utama, yakni prapemilu, pemilu, dan pascapemilu. Dalam periode pascapemilu, tugas KPU adalah menyampaikan laporan evaluasi kepada pemangku kepentingan yang juga memuat usulan pengubahan peraturan dan manajemen teknis kepemiluan untuk pemilu setelahnya.
“Namun tidak ada satupun yang mengusulkan perubahan implementasi dan pengaturan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar Bacaleg tiap Dapil yang dipraktekkan pada pemilu sebelumnya,” kata Titi.
Akademisi Universitas Jayabaya, R. Valentina Sagala selaku ahli pun membacakan pandangannya menjelaskan, bahwa kepentingan mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan setiap hak-haknya sebagai manusia. Untuk itu Hak Asasi Manusia (HAM) adalah naskah inti dalam Undang-Undang negara modern, yang juga terdapat di berbagai instrumen HAM yang diakui secara global.
Melalui perjuangan panjang, lanjut Valentina, pada tahun 1979 PBB mengadopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk-bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan.
“Melalui Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) memberikan definisi yang jelas tentang diskriminasi terhadap perempuan dan kesetaraan,” tutur Valentina, di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat.
Kemudian Indonesia mengesahkan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, Tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam UU tersebut menurut Valentina, mengandung prinsip kesetaraan substantif, yang artinya mengakui perempuan berada pada posisi yang tidak setara dan karena itu harus diperlakukan secara berbeda untuk memperoleh manfaat dan hasil akhir yang setara.
“Konsepsi kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama sangatlah sejalan dengan konstitusi kita. Jadi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen, yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 adalah upaya nyata untuk memperoleh kesempatan dalam bidang parlemen,” terangnya.
“Dengan kata lain, integritas dan profesionalitas KPU yang berpedoman pada prinsip jujur, mandiri, adil, akuntabel dan berkepastian hukum, semestinya tidak melahirkan pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023,” imbuhnya.
Ahli lainnya, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada, Abdul Gaffar Karim mengatakan, KPU terikat dengan etika politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurutnya, KPU adalah kanal untuk memastikan kegelisahan masyarakat sipil dapat sampai ke ranah negara dan dapat terjaga sampai ke sana.
“KPU adalah representasi civil society di ranah negara, yang seharusnya masih memperhatikan terkait penyelenggaraan pemilu yang ideal dan membuktikan independensi terhadap partai politik,” kata Gaffar.
Sayangnya, lanjut Gaffar, di Indonesia dewasa ini yang berlangsung adalah relasi antara penyelenggara pemilu, lembaga negara, dan kekuatan elektoral. Problem sebenarnya terletak pada State Auxiliary Agencies (SAA) yang menjauhkan penyelenggara pemilu dari masyarakat sipil dan membawanya ke titik tengah di aras negara.
“SAA pada prakteknya tidak dirancang menjadi kanal, ia hanya menjadi sumber recruitment saja, bukan sumber moral. Kita di ruangan ini paham, siapa mewakili apa,” ucap Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.
Belakangan ini, sambung Gaffar, nuansa militerisme terasa menguat di lembaga kepemiluan. Jika kita ingin menguatkan orientasi penyelenggara pemilu pada masyarakat sipil kita memerlukan penataan yang lebih mendasar terkait SAA di Indonesia.
Tiga ahli tersebut dihadirkan oleh Pengadu yang merupakan kelompok bernama Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. Koalisi ini terdiri dari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mikewati Vera Tangka; Ketua Yayasan Kalyanamitra, Listyowati; Direktur INFID, Misthohizzaman; dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan anggota Bawaslu RI Periode 2008-2012, Wirdyaningsih; Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay.
Teradu dalam dugaan pelanggaran kode etik tersebut merupakan tujuh anggota KPU. Satu anggota sekaligus Ketua KPU adalah Hasyim Asy’ari. Enam anggota KPU yang lain adalah Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Mochammad Afifuddin.
Tujuh anggota KPU tersebut diadukan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengenai kesalahan cara menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR/DPRD dalam Pasal 8 Ayat (2) PKPU 10/2023. Melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) ketentuan ini pun telah terbukti melanggar Undang-Undang 7/2017, sehingga Pengadu memohon DKPP memberikan sanksi pemberhentian tujuh anggota KPU. []
AJID FUAD MUZAKI