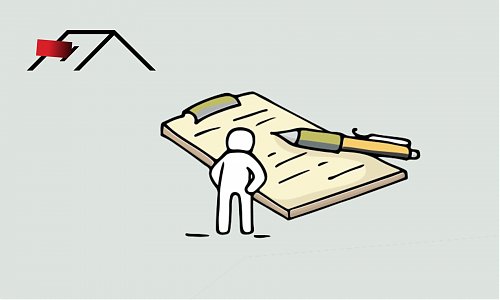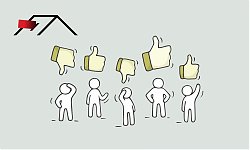Politik di Indonesia tengah diramaikan (lagi) dengan isu sistem pemilu, antara proporsional terbuka atau tertutup. Sistem pemilu proporsional terbuka yang termuat di dalam Undang-Undang (UU) Pemilu No.7/2017 digugat oleh salah satunya pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Demas Brian Wicaksono. Sistem proporsional terbuka dinilai para pemohon bertentangan dengan Pasal 22E ayat (3) UU Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPR Daerah (DPRD) ialah partai politik.
Perdebatan tersebut makin menghangat dengan terlibatnya berbagai pihak sebagai pihak terkait dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) salah satu organisasi masyarakat sipil yang mengajukan diri sebagai pihak terkait.
Kelompok perempuan pun ikut mendiskusikan dampak sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup terhadap keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam diskusi “Menavigasi Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup” (8/3), kelompok aktivis perempuan politik urun rembuk.
Dalam diskusi tersebut, akademisi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan bahwa pilihan sistem pemilu haruslah berangkat dari tujuan pemilu yang ingin dicapai, misalnya mengefektifkan pemerintahan dan meningkatkan keterwakilan perempuan. Tujuan pemilu tak dicantumkan di dalam UU Pemilu No.7/2017.
“Pasal 4 UU Pemilu tidak bicara tujuan pemilu. Hanya bicara tujuan pengaturan pemilu. Harusnya tujuan pemilu. Misal, apakah pemilu ingin dibangun untuk mengefektifkan pemerintahan, atau juga misal keterwakilan perempuan. Di UU No.12/2003 disebutkan tujuan soal keterwakilan perempuan, tetapi justru di UU No.7/2017 bergeser,” jelas Titi.
Selain tujuan pemilu, pemilihan sistem pemilu juga idealnya memperhatikan sepuluh hal. Satu, memperhatikan representasi atau keterwakilan. Dua, membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna. Tiga, memungkinkan perdamaian. Empat, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil. Lima, pemerintah yang terpilih akuntabel. Enam, pemilih mampu mengawasi wakil terpilih. Tujuh, mendorong partai politik bekerja lebih baik. Delapan, mempromosikan kontrol oleh legislatif. Sembilan, mampu membuat proses pemilu berkesinambungan. Sepuluh, memperhatikan standar internasional.
Tak setuju sistem pemilu diputuskan MK
“Terlalu kompleks kalau sistem pemilu diserahkan kepada MK, karena sistem pemilu itu membawa konsekuensi-konsekuensi teknis yang detil, yang tidak akan bisa dirumuskan oleh 9 hakim konstitusi dalam proses judisialisasi politik yang mereka tangani,” tandas Titi.
Pilihan sistem pemilu membawa dampak teknis. Putusan MK No.22,24 tahun 2008 yang memberlakukan sistem proporsional terbuka tak menyentuh variabel teknis seperti sinkronisasi metode pemberian suara dan implikasi pemberian suara yang masih memperbolehkan tanda gambar partai.
“Sayangnya KPU (Komisi Pemilihan Umum)nya juga waktu itu tidak memberikan detail teknis soal implikasi teknis dari permohonan para pemohon ini,” pungkas Titi.
Merujuk Buku 5 pembahasan Pemilihan Umum amandemenen konstitusi, sistem pemilu DPR dan DPRD tak ditentukan di dalam konstitusi karena keputusan terkait sistem pemilu tak mendapatkan persetujuan bulat. Dengan demikian, konstitusi memberikan fleksibilitas kepada pembentuk undang-undang. Konstitusi hanya secara jelas menentukan sistem pemilu presiden.
“Saya tidak mendukung MK menentukan sistem pemilu, karena itu bisa jadi jebakan bagi kita. Karena MK, di tengah ratusan sistem, bisa terjebak menyatakan ini yang konstitusional atau tidak, dan kita justru akan kesulitan di masa yang akan datang, harus melakukan penyesuaian atau terobosan,” tegas Titi.
Ia meyakini bahwa MK tak akan mengabulkan permohonan sistem pemilu yang diajukan. Tren konsistensi MK selama ini, sistem pemilu dinilai MK sebagai open legal policy.
Masalah mendasar keterwakilan perempuan ialah sistem politik
Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI), Anna Margret, menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan bukanlah sistem pemilu, melainkan sistem politik yang tak berpihak pada prinsip kesetaraan. Penguatan partai politik dan politik perempuan diperlukan untuk dapat meningkatkan representasi perempuan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
“Jadi, mau apa pun sistem pemilunya, kalau dijalankan pada sistem politik yang tidak berpihak pada kesetaraan, susah. Kalau sistem tertutup, kita harus punya relasi amat sangat baik dengan partai, karena yang menentukan adalah partai. Kalau sistem terbuka, politik uang marak, tetapi dalam politik, politik uang itu suatu keniscayaan. Hanya beda dalam bentuk, skala, dan akses media dalam menjangkau fenomenanya,” terang Anna.
Meski demikian, Anna menunjukkan bahwa dalam pemilu dengan sistem pemilu proporsional terbuka, persentase suara perempuan terus meningkat. Pada Pemilu 2009, perempuan calon anggota legislatif (caleg) memperoleh suara 22 persen. Pemilu 2014, 23 persen. Pemilu 2019, 24,01 persen. Data tersebut menggambarkan bahwa perempuan memiliki legitimasi kuat dari pemilih. Pemilih memilih memberikan suara langsung kepada perempuan caleg dibandingkan kepada partai politik.
“Kelihatannya tipis meningkatnya, tapi ini tren positif karena naik terus. Sekarang kita harus arahkan kepada politik perempuan yang transformatif,” ungkapnya.
Per 8 Maret 2023, persentase keterwakilan perempuan di DPR RI ialah 20,52 persen. Jumlah perempuan anggota DPR RI meningkat dengan adanya penggantian anggota antar waktu.
Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Lena Maryana Mukti menekankan agar perempuan siap dengan sistem pemilu apa pun. Yang terpenting yakni, mengurus daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk terus menjaga kedekatan dengan konstituen.
“Kesiapan perempuan caleg menghadapi Pemilu 2024 juga harus diurus. Jangan dipusingkan dengan sistem pemilu. Karena, susahnya kita, kita tidak punya cukup kekuatan di parlemen untuk mengatur undang-undang yang memberikan manfaat lebih banyak bagi representasi perempuan di parlemen,” tutup Lena. []
AMALIA SALABI