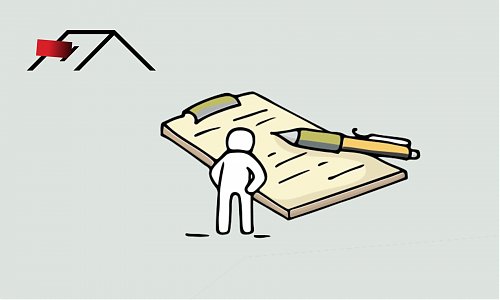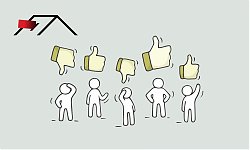Kemandirian dan kehormatan semestinya dua hal yang berjalan seiring bagi penyelenggara pemilu. Kemandirian lebih bersifat institusional sedangkan kehormatan lebih bersifat individual. Untuk menjaga kemandirian lembaganya, anggota penyelenggara pemilu menjaga kehormatan berdasarkan kode etik penyelenggara pemilu. Penyimpangan dan pengabaian salah satunya, bisa merusak satu yang lainnya. Ketidakmandirian akan dibenarkan dengan pelanggaran etik. Sebaliknya, pelanggaran etik bisa berdampak pada ketidakmandirian.
Tapi, dalam beberapa peristiwa kepemiluan Indonesia menunjukan, keduanya bisa kurang seiring. Di antaranya dalam tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu. Pertaluan kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu coba digambarkan dalam sidang etik penyelenggara pemilu yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pengaduan dugaan pelanggaran etik dalam tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024 seperti pengulangan dengan Pemilu 2014. Perbedaannya, pada 2024, Pengadu adalah anggota KPU di daerah, sedangkan pada 2014, Pengadu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian, pada 2024, yang diadukan merupakan tindakan anggota KPU yang secara hierarkis merekayasa kepesertaan pemilu, sedangkan pada 2014, yang diadukan merupakan tindakan anggota KPU yang menggunakan sistem informasi partai politik (Sipol) dalam verifikasi partai politik.
Secara umum, peradilan etik pemilu melalui DKPP bisa menjawab kebutuhan jaminan kemandirian KPU. Tapi, pada konteks tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu, kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu punya tantangan amat berat untuk dijamin utuh secara bersamaan.
Penyebab dari catatan itu justru ada dalam undang-undang pemilu. Kewajiban taat hukum bagi penyelenggara pemilu malah bermasalah karena pada dasarnya undang-undangnya bermasalah. Pemilu Indonesia punya syarat pendaftaran partai politik yang amat berat.
Pembentukan partai politik dan kepesertaannya di pemilu merupakan hak asasi manusia (HAM) bidang politik bagi warga yang harus dijamin kebebasannya secara konstitusional. Tapi malah, partai berkuasa di DPR dan pemerintah, membuat syarat pembentukan dan kepesertaan partai di pemilu. Partai politik harus punya kantor dan anggota di seluruh provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Syarat amat berat ini bukan hanya amat menyulitkan partai politik tapi juga para anggota penyelenggara dan petugas pemilu dalam pengadministrasian dan pembuktian.
Setidaknya, ada dua konsekuensi dari persyaratan amat berat dalam kepesertaan partai politik. Pertama, pembajakan partai politik. Kedua, kolusi dan korupsi. Pembajakan partai politik berarti terputusnya fungsi representasi dan aspirasi rakyat beralih ke pemimpin/elite partai politik dan pemilik modal. Kolusi dan korupsi berarti, partai terdorong melakukan berbagai cara, termasuk menyuap penyelenggara dan petugas pemilu, agar bisa lolos menjadi peserta pemilu. Atau sebaliknya, kolusi dan korupsi terjadi karena penyelenggara dan petugas pemilu sadar kewenangannya menentukan hidup/mati partai politik.
Pada konteks Pemilu 2014, KPU coba menjamin kemandirian dan kehormatan dengan menghindari dua konsekuensi tersebut melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Format digital Sipol diyakini bisa mengatasi beban administratif dokumen cetak dalam verifikasi partai politik yang amat berat. Sayangnya, penggunaan Sipol ini membuat para anggota KPU diadukan ke DKPP karena melakukan pelanggaran etik. Oleh partai politik DPR, Sipol dinilai telah melampaui undang-undang. Lalu, Sipol pun dinilai sebagai teknologi asing yang bisa mengancam kemandirian KPU.
Berbeda dengan konteks Pemilu 2024, KPU malah tidak mengoptimalkan Sipol dalam mengatasi kompleksitas verifikasi partai politik. Dalam pemberitaan di media massa serta sidang pembuktian dan kesaksian yang diselenggarakan DKPP, dijelaskan bahwa, anggota KPU pusat secara hierarkis meminta KPU di daerah meloloskan partai politik untuk menjadi peserta pemilu, meski ada yang tidak memenuhi syarat.
Dari dua peristiwa tersebut, ada perbedaan cara dari KPU dalam menyikapi benturan antara hak politik dengan syarat kepesertaan pemilu yang amat berat. KPU pusat pada Pemilu 2014, mencoba menjaga kemandiriannya berdasarkan kode etik untuk menyiasati undang-undang. Sedangkan KPU pusat pada Pemilu 2024, mengatasnamakan kemandiriannya melalui penyimpangan kode etik kehormatan dan undang-undang. Perbedaan cara ini yang kemudian menggambarkan perbedaan kualitas kemandirian KPU.
Perbedaan makna kemandirian
Cara pelanggaran dan kualitas kemandirian KPU tersebut bisa dibedakan karena pada dasarnya ada perbedaan makna kemandirian penyelenggara pemilu. Bisa jadi perbedaan makna di sini disebabkan oleh perbedaan pemahaman, bahkan mungkin paham, para pemangku kepentingan pemilu Indonesia.
Kemandirian penyelenggara pemilu dijamin kokoh dalam peraturan perundangan-undangan Indonesia. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan kata mandiri sebagai salah satu sifat dari komisi pemilihan umum. Ketentuan konstitusi ini kemudian diturunkan pada Pasal 1 angka 8 UU 7/2017 yang bertuliskan, Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
Secara hierarkis dan positivistik, komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri adalah KPU. UU 7/2017 tidak menyertakan sifat nasional, tetap, dan mandiri dalam pengertian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP.
Pasal 7 ayat (3) UU 7/2017 secara tidak langsung memberikan penjelasan makna kemandirian KPU. Bunyinya, dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bunyi ini sebetulnya sesuai dengan konsensus original intent Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 meski kemudian kemandirian KPU pada Pemilu 2004 diwujudkan dengan keanggotaan profesional nonpartai politik beserta kewenangan utuh dalam pembentukan daerah pemilihan, penyelenggaraan, dan anggaran.
UU 7/2017 pun menghubungkan kemandirian dengan kehormatan. Pasal 157 ayat (1), mempunyai penekanan, DKPP menyusun dan menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas semua anggota penyelenggara pemilu dengan seluruh tingkatannya. UU 7/2017 hanya mempunyai dua kata “kehormatan” yang ditujukan bagi DKPP dan lima kata “hormat” untuk menekankan pemberhentian tidak hormat sebagai sanksi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.
Kehormatan penyelenggara pemilu tidak mempunyai rujukan dalam undang-undang dasar. Hanya undang-undang kepemiluan yang menjadi dasar utama kehormatan penyelenggara pemilu bersama kelembagaannya. Sebelum UU 7/2017, kehormatan penyelenggara pemilu dan kelembagaannya dijamin UU 12/2003 dengan lembaga bersifat ad-hoc bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lalu, dalam UU 15/2011 DK-KPU berubah menjadi DKPP sebagai lembaga yang bersifat tetap.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) dalam beberapa publikasinya memaknai kemandirian KPU secara berbeda. Lembaga riset kepemiluan ini membagi tiga model lembaga penyelenggara pemilu. Pertama, Independent Model. Kedua, Governmental Model. Ketiga, Mixed Model (Catt, 2014).
Independent Model berarti punya sejumlah aspek kemandirian. Kemandirian yang ditekankan International IDEA di antaranya adalah kewenangan membuat peraturan, komposisi keanggotaan bukan dari unsur pemerintahan (triaspolitika), masa jabatan kerja penyelenggara yang pasti, dan penganggaran yang menjamin siklus kepemiluan.
Lalu bagaimana pengertian Governmental Model dan Mixed Model? Penjelasan singkatnya yaitu: semakin banyak aspek-aspek tersebut diintervensi oleh pemerintahan (triaspolitika), maka model lembaga penyelenggara pemilu semakin menjadi Governmental Model. Lalu, semakin banyak aspek-aspek tersebut dicampurkan mana yang diintervensi oleh pemerintahan, dan aspek mana yang mandiri (nonpemerintah), maka ini akan menjadi Mixed Model.
Dari perbedaan makna kemandirian tersebut, sikap KPU dalam verifikasi partai politik Pemilu 2014, sesuai dengan makna kemandirian menurut peraturan perundang-undangan dan seusia dengan makna kemandirian menurut International IDEA. Tapi, dari kedua pemaknaan ini, KPU pada konteks Pemilu 2014 lebih dekat pada makna kemandirian menurut International IDEA.
Berdasarkan makna kemandirian itu, penggunaan Sipol pada verifikasi partai politik Pemilu 2014, bukan merupakan penyimpangan kemandirian penyelenggara pemilu. Menggunakan Sipol sebagai alat bantu hasil dari studi dan implementasi internasional, bukan merupakan intervensi kemandirian KPU. Paham ultranasionalisme akan memaknai ini sebagai bentuk intervensi asing yang merusak kemandirian KPU bahkan kedaulatan negara. Padahal, bagi International IDEA, intevensi DPR dan pemerintah dalam wujud unsur, arahan, dan kewenangan, merupakan inti dari antitesis model KPU yang mandiri.
Sedangkan sikap KPU dalam verifikasi partai politik Pemilu 2024, tidak sesuai dengan makna kemandirian mana pun. KPU pada konteks ini tidak sesuai kemandirian dalam peraturan perundang-undangan, karena mengabaikan syarat kepesertaan pemilu yang tidak dipenuhi. Ini pun tidak sesuai dengan makna kemandirian International IDEA karena ketidakjelasan motif dari KPU dalam meloloskan semua partai politik, menyertai rumor intervensi partai pemerintah yang ingin memecah partai oposisi melalui partai-partai baru. Rumor motif ini bisa dihubungkan dengan peristiwa pemilihan anggota KPU(-Bawaslu) yang tertutup sebagai wujud pemilihan anggota KPU yang tidak sesuai dengan makna kemandirian.
Mengubah syarat kepesertaan partai
Agar benturan kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu ini tidak lagi terjadi dalam verifikasi partai politik peserta pemilu, syarat yang sekarang berlaku harus diubah. Sidang etik DKPP terhadap anggota KPU pusat pada Pemilu 2014, jangan dilupakan untuk menjadi evaluasi. Lalu, sidang etik terhadap anggota KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota pada Pemilu 2024, harus jadi momentum kesadaran nasional pentingnya merevisi syarat kepesertaan partai politik dalam undang-undang pemilu.
Jika dibanding dengan negara-negara lain, syarat kepesertaan partai politik di Indonesia merupakan syarat yang termasuk paling berat dan kompleks. Di Australia misalnya, partai politik cukup punya minimal 1.500 anggota yang termasuk dalam daftar pemilih, atau partai politik cukup punya minimal satu Senator atau Anggota DPR yang menjabat. Indonesia pun pada Pemilu 1999 punya syarat kepesertaan yang ringan dan sederhana yaitu, partai politik cukup punya minimal 50 orang anggota.
Selebihnya, verifikasi partai politik harus dibuat secara objektif, yaitu syarat yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik. Syarat ini objektif karena tidak bias partai politik besar/kecil, lama/baru, dan dalam/luar parlemen. Syarat ini pun objektif karena memang menentukan baik/buruk partai politik dan relevan dengan fungsi pemilu untuk mengevaluasi pemerintahan menjadi lebih baik dan bersih dari korupsi.
Syarat objektif tersebut menyertakan proses perubahan syarat kepesertaannya, memang tidak bisa berlaku untuk Pemilu 2024. Biar kemudian putusan DKPP dan perbaikan internal anggota KPU yang memastikan kualitas kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu. Tapi, jika syarat kepesertaan partai politik tetap terlalu berat, selamanya kemandirian dan kehormatan penyelenggara pemilu akan selalu dipertaruhkan dalam tahapan verifikasi partai politik. []
USEP HASAN SADIKIN