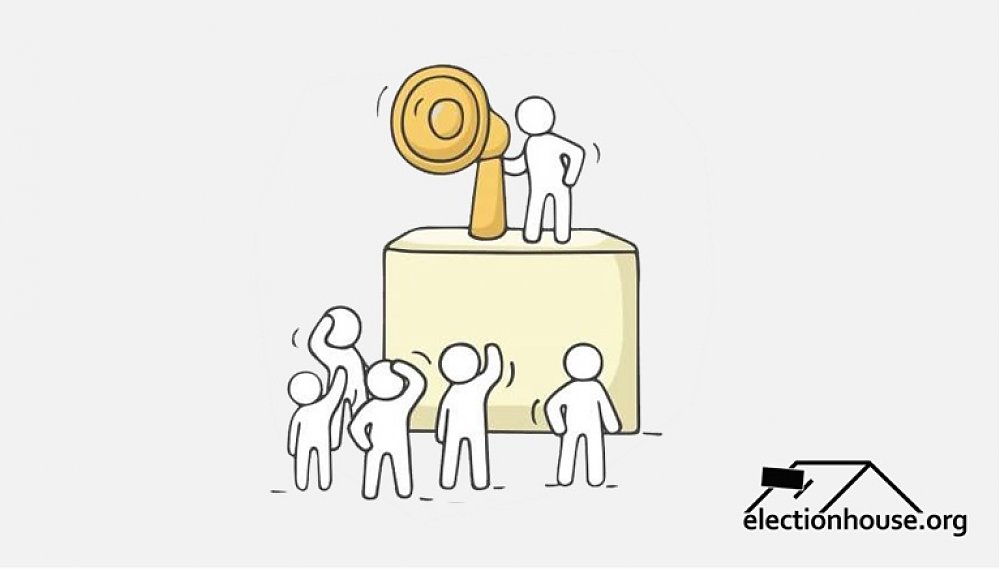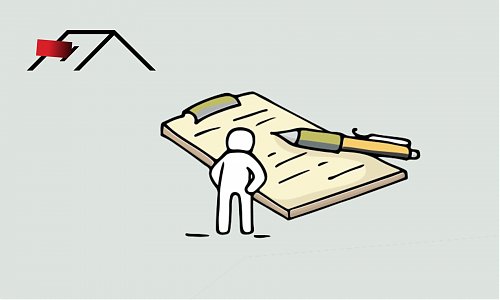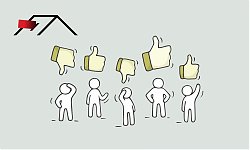Kompleks Industrial Pemilu Indonesia belum pernah sekuat ini. Setiap siklus pemilu selama dekade terakhir telah menampakkan peningkatan dalam penggunaan para kontraktor untuk menjalankan unsur-unsur kampanye politik, terutama di pemilu presiden dan gubernur.[1]
Para contractor ini menawarkan layanan mulai dari strategi hubungan masyarakat hingga pemantauan media social, dan yang paling kontroversial adalah menjadi ‘buzzer’. Saya akan menganalisis aspek terakhir Kompleks Industrial Pemilu ini. Setelah membedah anatomi industri buzzer dan menyajikan suatu analisis moral, saya berpendapat bahwa agensi yang mempekerjakan buzzer harus lebih dipertimbangankan dalam pembahasan kebijakan. Saya akan mengusulkan solusi baru yang terinspirasi dari perkembangan di Australia dan Uni Eropa: perkembangan Pedoman Praktik pengaturan mandiri dalam kemitraan dengan lembaga-lembaga ini. Pedoman ini akan mempercepat pemberantasan disinformasi dan serangan terhadap SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), unsur buzzer yang paling merusak. Solusi ini memiliki kelemahan tetapi perlu dipertimbangkan, karena rangkaian tanggapan kebijakan saat ini terhadap buzzer sangat tidak memadai.
Pemilihan pertama yang melibatkan kampanye terkoordinasi berskala besar di media sosial adalah Pilkada DKI Jakarta 2012, yang mempertemukan Joko ‘Jokowi’ Widodo melawan petahana Fauzi Bowo.[2] Keberhasilan Jokowi pada 2012 dilanjutkan hingga kampanye Presiden 2014 dengan meningkatnya penggunaan buzzer.[3] Pradipa P. Rasidi mencatat bahwa pertama-tama buzzer menjadi figur yang terkenal dalam pemilu itu, yang di dalamnya mereka terkenal dengan sebutan panasbung, singkatan dari pasukan nasi bungkus dan panastak atau pasukan nasi kotak.[4] Peran buzzer dalam pemilu terus berkembang dengan Basuki Tjahaja Purnama, atau ‘Ahok’, yang mencalonkan diri kembali pada 2017. Kampanye tersebut, bertepatan dengan Gerakan 212, memperlihatkan peningkatan penyebaran SARA oleh para buzzer untuk menyerang Ahok yang beragama Kristen dan keturunan Tionghoa.[5] Pemilu Presiden 2019 menunjukkan berlanjutnya tren ini, dengan para buzzer yang mendukung kedua pasangan calon supporting both tickets.[6] Dengan pemilu presiden dan pemilu gubernur yang bersamaan pada tahun 2024, kemungkinan besar Komplek Industrial Pemilu akan mencapai ketinggian yang baru secara keseluruhan.[7]
Anatomi Industri Buzzer
Tidak ada definisi buzzer yang telah disepakati secara akademis. Sebagian besar definisi konventional menggambarkan buzzer sebagai ‘seseorang yang menyebarkan pendapat tertentu tentang isu atau merek tertentu, dengan harapan jangkauan audiens yang luas.[8] Namun, terdapat perdebatan, apakah buzzer dapat bersifat sukarela atau apakah mereka harus diberi kompensasi finansial, dan apakah akun-akun anonim harus dimasukkan dalam definisi ‘buzzer’.[9] Untuk menghindari perdebatan definisi yang pada akhirnya tidak signifikan, makalah ini akan mengikuti contoh Rasidi dalam mengambil pendekatan yang paling luas – termasuk pengguna sukarela dan non-anonim. Perlu juga disebutkan bahwa buzzer pertama kali muncul dalam pemasaran komersial daripada kampanye politik, meskipun bagian ini berkaitan dengan yang terakhir
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak akademisi berusaha menganalisis industri buzzer politik dari berbagai perspektif. Dari literatur yang berkembang, beberapa pengamatan umum dapat dilakukan. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, biasanya ada lapisan tengah antara klien dan buzzer itu sendiri. Meskipun ini dapat mengambil banyak bentuk, makalah ini akan merujuk pada lapisan tengah ini secara kolektif sebagai 'agen pemasaran media sosial' – yang biasanya menawarkan buzzer sebagai bagian dari rangkaian layanan pemasaran/humas. Harus dicatat bahwa ada beberapa lapisan menengah yang tidak sesuai dengan pengamatan ini, contoh utamanya adalah Teman Ahok – sebuah organisasi sukarela yang didirikan oleh para aktivis pro-Ahok.[10] Memang, seringkali kampanye politik merekrut dan mengelola sukarelawan buzzer secara langsung. Meskipun demikian, Kompleks Industrial-Pemilu Indonesia tampaknya didominasi oleh agen-agen pemasaran.[11]

Gambar 1: Struktur Industri Buzzer[12]
Pengamatan penting lainnya dari literatur ini berkaitan dengan individu yang terlibat dalam operasi buzzer ini. Dua pola dasar telah muncul.[13] Pola dasar pertama yang dapat kita sebut sebagai 'penganut sejati' – pendukung sah dari klien buzzer mereka. Terlepas dari apakah mereka dibayar, para buzzer ini melihat pekerjaan mereka sebagai tindakan politik yang berarti untuk mendukung kandidat yang mereka anggap lebih unggul secara moral daripada oposisi mereka. Pola dasar kedua yang bisa kita sebut 'penipu netral' - pekerja yang termotivasi secara finansial yang melihat buzzer mereka hanya sebagai sumber pendapatan tambahan. Dalam kedua kasus tersebut, demografi utama tampaknya adalah orang dewasa muda perkotaan, seringkali berpendidikan universitas dan sadar politik (setidaknya untuk 'penganut sejati'). Pada kenyataannya, tentu saja, individu mungkin berada di antara kedua pola dasar ini, atau bahkan berpindah dari satu pola dasar ke pola dasar lainnya. Bagaimanapun, penting untuk mengingat motivasi ini karena kami mempertimbangkan moralitas industri buzzer secara luas.
Analisis Moral
Hal pertama yang harus ditetapkan adalah bahwa buzzer tidak dapat langsung dianggap tercela secara moral. Kampanye politik jelas merupakan komponen dari demokrasi yang sehat, karena perannya dalam mempromosikan keterlibatan pemilih dan akuntabilitas. Voluntarisme politik memang sering diromantisasi sebagai representasi semangat demokrasi yang kuat.[14] Terlebih lagi, metode kampanye komersial lainnya (iklan TV, baliho, dll) diterima secara luas sebagai bagian tak terelakkan dari pemilu yang bebas. Paling buruk, ini hanyalah gangguan belaka. Industri buzzer seharusnya tidak diperlakukan berbeda secara radikal. Sulit untuk membedakan antara tim sukarelawan pengetuk pintu yang diberi poin pembicaraan utama dan tim pengguna media sosial yang menyebarkan pesan yang sama. Selain itu, makalah Rasidi berargumen bahwa banyak buzzer – pola dasar ‘penganut sejati’ – menemukan agensi politik dalam peran mereka.[15] Agensi seperti itu seharusnya dinilai karena menangkal pencabutan hak, sinisme, dan fatalisme.
Akan tetapi, ada juga unsur-unsur buzzer yang tak dapat disangkal lagi sebagai tidak bermoral. Unsur buzzer yang tercela ini dapat dibagi dalam dua kategori: 1) disinformasi, dan 2) serangan terhadap SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Tujuan dari disinformasi adalah untuk secara terang-terangan memanipulasi warga agar memilih dengan cara tertentu, seringkali memiliki efek polarisasi dalam prosesnya. Untuk SARA, sekali lagi, hasilnya adalah meningkatnya polarisasi. Akan tetapi, di sini atas dasar identitas, dengan potensi yang nyata untuk berubah menjadi kekerasan. Jelasnya, kebanyakan konten yang disebar buzzer adalah kritik atau pujian politik konvensional. Sangat mungkin bagi buzzer untuk beroperasi tanpa menyebarkan disinformasi atau SARA; sekalipun di dalam industri, konten semacam itu dipandang sebagai tindakan ekstrem. Kembali ke analogi para pengetuk pintu, jika para relawan ini disuruh berkeliling dari rumah ke rumah menyebarkan disinformasi dan SARA, jelas diperlukan intervensi. Ini tidak berarti bahwa pengetuk pintu secara umum harus dilarang, tetapi langkah-langkah harus diambil untuk mengatur perilaku para pengetuk pintu itu. Buzzer adalah kasus serupa: masyarakat sipil tidak dapat secara realistis mengejar pemberantasan buzzer secara langsung (dan mungkin seharusnya tidak), tetapi mereka harus mendorong langkah-langkah untuk membatasi konten yang disebarkan oleh buzzer.
Analisis Kebijakan
Tantangan peraturan utama yang ditimbulkan oleh industri kampanye politik adalah bahwa pendirian politik adalah penerima manfaat utama dari industri ini. Para pemimpin politik tidak mungkin tertarik untuk melegitimasi keuntungan elektoral. Bahkan jika Pemerintah benar-benar mengusulkan undang-undang yang mengatur industri ini, kemungkinan besar itu hanya akan digunakan untuk melawan kampanye oposisi (lihat, misalnya, UU ITE).
Oleh karena itu penting untuk melihat di luar peraturan konvensional untuk solusi atas masalah yang ditimbulkan oleh buzzer. Sebagian besar analisis kebijakan berfokus pada disinformasi atau SARA secara umum, bukan buzzer secara khusus, sehingga cenderung hanya mempertimbangkan dua tanggapan: 1) memberdayakan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya atau disinformasi, atau 2) meningkatkan literasi digital publik.[16] Akan tetapi, munculnya disinformasi belum dapat ditekan, dan respons regulasi yang ada telah menimbulkan masalah lain.[17] Jelas, perlu untuk mengeksplorasi solusi baru. Laporan ini menyajikan satu gagasan seperti itu: pengaturan mandiri industri buzzer.
Pengaturan mandiri disinformasi secara luas (yaitu, di luar isu khusus buzzer), bukanlah ide yang sepenuhnya baru. Baik Australia[18] maupun Uni Eropa[19] telah mengembangkan Pedoman Praktik Disinformasi. Perusahaan media sosial menjadi sasaran dalam kedua kasus tersebut (walaupun OMS juga merupakan penandatangan Pedoman UE), dengan tujuan utama mendorong perusahaan tersebut untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi. Namun dalam kedua kasus tersebut, Pedoman Praktik disesuaikan dengan konteks politik yang berbeda dengan yang dihadapi oleh Indonesia. Seperti dibahas di atas, disinformasi di Indonesia tidak hanya disebarkan oleh individu-individu yang terputus dan anonim, tetapi juga oleh jaringan buzzer yang sangat terkoordinasi dan terlembaga. Untuk menekan bentuk disinformasi ini, Pedoman Praktik Indonesia perlu menyasar buzzer secara langsung.
Gagasannya sebagai berikut. Masyarakat sipil Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan marketing digital untuk mengembangkan Pedoman Praktis Kampanye Digital. Untuk menandatangani Pedoman ini, perusahaan harus memenuhi dua persyaratan utama. Pertama, mereka harus menerima larangan menyebarkan disinformasi dan SARA. Kedua, mereka harus mengadopsi langkah-langkah yang cukup transparan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap larangan itu. Auditor harus diberdayakan untuk secara rutin memeriksa sampel konten secara acak yang disebarkan oleh para buzzer masing-masing perusahaan itu. Persyaratan ini harus ditentukan secara ketat dengan tahap pelaksanaan (misalnya merinci kualifikasi SARA), yang ditentukan setelah berkolaborasi dengan perusahaan sasaran. Kedua persyaratan ini dapat dianggap mahal, dan dengan demikian upaya harus dilakukan untuk meminimalkan biaya yang dirasakan ini tanpa merusak keefektifan Pedoman.
Mengingat motivasi altruistik tidaklah mungkin, mengapa agensi bergabung dengan Pedoman Praktik? Pedoman yang dirancang dengan benar harus menarik perusahaan yang didorong oleh keuntungan yang paling sinis sekalipun. Menjadi penandatangan Pedoman akan memberikan publisitas positif kepada perusahaan. Perusahaan tersebut akan menonjol bagi para politisi yang mencari kontraktor tepercaya dan andal dalam industri yang suram. Manfaat lain untuk bergabung dengan Pedoman ini adalah merekrut buzzer sendiri. Ada kemungkinan individu akan lebih bersedia bekerja untuk perusahaan yang membutuhkan lebih sedikit kompromi moral. Selain itu, perusahaan buzzer memiliki reputasi sebagai pemberi kerja yang tidak dapat diandalkan yang rentan terhadap pembayaran gaji yang terlambat atau tidak lengkap. Menandatangani Pedoman ini akan menyiratkan tingkat kredibilitas yang akan meyakinkan calon karyawan. Terakhir, para buzzer dan perusahaannya akan memiliki nurani. Karyawan dalam industri dapat secara masuk akal menekan organisasi mereka untuk menandatangani Pedoman Praktik.
Pembenaran ini bukan hanya spekulasi kosong, melainkan didukung oleh contoh Pedoman Praktik di Australia dan Uni Eropa. Keduanya berhasil menarik semua perusahaan media sosial besar, mungkin karena alasan yang diuraikan di atas. Sementara perusahaan tidak harus menandatangani semua komitmen (lihat Gambar 2), mereka semua dengan jelas menemukan pembenaran yang cukup untuk berpartisipasi dalam Pedoman ini dalam beberapa kapasitas. Ini menjadi preseden yang sangat menggembirakan.

Gambar 2: Komitmen Spesifik, Pedoman Praktik Disinformasi Australia[20]
Meskipun demikian, ada alasan untuk meyakini bahwa Kode Praktik yang ditargetkan oleh buzzer mungkin kurang berhasil dibandingkan versi Australia dan Uni Eropa. Politisi sangat enggan mengakui menggunakan buzzer (lihat, misalnya, kampanye Anies Baswedan pada 2017).[21] Menandatangani Pedoman Praktik mungkin dapat membuat agensi kurang menarik bagi kandidat politik yang lebih memilih untuk bermitra dengan agensi dengan profil publik yang rendah. Hal ini dapat dikurangi dengan menghindari pembingkaian pedoman sebagai 'Pedoman Praktik Buzzer melainkan sebagai 'Pedoman Praktik Kampanye Digital'. Namun, satu-satunya cara untuk sepenuhnya mencegah hasil ini adalah dengan mengembangkan Pedoman bekerja sama dengan lembaga dan, idealnya, kandidat itu sendiri. Dengan begitu, industri dapat diyakinkan kembali bahwa Pedoman ini hanya memberikan keuntungan reputasi, bukan kerugian.
Pendekatan kolaboratif ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada keunggulan kompetitif yang hilang dengan mengikuti Pedoman ini. Perusahaan akan enggan menjadi penandatangan pertama Pedoman Praktik, karena khawatir perusahaan lain akan terus menggunakan disinformasi dan SARA untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Ketakutan penggerak pertama ini tidak hanya berlaku untuk ajakan untuk bergabung dalam proses pengembangan kebijakan kolaboratif, karena proses seperti itu bukanlah sebuah komitmen. Setelah cukup banyak agensi, secara metaforis, berada di dalam ruangan, kemungkinan besar mereka dapat secara kolektif setuju untuk secara bersamaan bergabung dengan pedoman tersebut.
Selain itu, akan sangat ideal jika kandidat/kampanye politik itu sendiri (dan kampanye semi-tautan seperti Teman Ahok) menandatangani Pedoman Praktik. Jika tidak, maka Pedoman akan kehilangan segmen industri buzzer – buzzer yang dikontrak langsung ke/menjadi sukarelawan langsung untuk kampanye. Sulit untuk menilai kemungkinan masuknya kelompok-kelompok ini. Di satu sisi, semua argumen tentang publisitas positif berlaku. Namun, sekali lagi, kampanye politik cenderung takut akan hubungan apa pun dengan industri buzzer. Upaya pasti perlu dilakukan untuk mengundang kelompok-kelompok ini ke dalam proses desain kebijakan kolaboratif.
Terakhir, meskipun semua kekhawatiran sebelumnya telah diatasi, Pedoman Praktik tidak akan pernah dapat sepenuhnya mencegah buzzer menyebarkan disinformasi dan SARA. Tidak mungkin semua perusahaan buzzer akan menandatangani Pedoman ini, dan bahkan mereka yang melakukannya kadang-kadang melanggarnya. Dalam konteks Australia, misalnya, tanda-tanda awal menunjukkan bahwa Pedoman ini hanya akan cukup efektif.[22] Hal ini menyebabkan Pemerintah Australia mengumumkan kewenangan lebih lanjut untuk regulator pada bulan Januari.[23] Akan tetapi, setiap berkurangnya penyebaran disinformasi dan SARA adalah sebuah kemenangan, sehingga kelemahan terakhir ini tidaklah fatal.
Kesimpulan
Buzzers adalah dilema kebijakan yang membingungkan, yang terletak di perhubungan banyak tren makro: munculnya media sosial, kontrol politik perusahaan, ketegangan agama/budaya yang terpolarisasi, dan bahkan munculnya perekonomian gig. 12 bulan ke depan menjelang Pemilu 2024 ini dapat menentukan dan memberikan dorongan untuk tindakan cepat dan tegas oleh masyarakat sipil Indonesia. Sebagai bagian dari tindakan ini, Pedoman Praktik pengaturan mandiri untuk perusahaan marketing digital harus dipertimbangkan. Pedoman ini tidak akan menjadi obat mujarab, tetapi berpotensi mengecilkan peran buzzer dalam penyebaran disinformasi dan SARA – sebuah tujuan penting.
Daftar Pustaka
Australian Communications and Media Authority, Report to Government on the Adequacy of Digital Platforms’ Disinformation and News Quality Measures (2021) <https://www.acma.gov.au/report-government-adequacy-digital-platforms-disinformation-and-news-quality-measures>
Digital Industry Group Inc, Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation (2022) <https://digi.org.au/disinformation-code/>
European Commission, ‘The 2022 Code of Practice on Disinformation’, European Commission (online, 2022) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>
Gallander, Sebastian, ‘Why Volunteering Is the Pulse of Democracy’, TwentyThirty. (2018)
Idris, Ika, Laeeq Khan and Nuurrianti Jalli, ‘Indonesia’s Misinformation Army Ready for War in 2023’, tempo.co (2023)
Lamb, Kate, ‘“I Felt Disgusted”: Inside Indonesia’s Fake Twitter Account Factories’, The Guardian (2018)
Ningtyas, Ika, ‘Menguatnya Kontrol Negara Di Ruang Digital Dengan Dalih Memerangi Hoaks’, Remotivi (online, 2023) <https://www.remotivi.or.id/amatan/800/menguatnya-kontrol-negara-di-ruang-digital-dengan-dalih-memerangi-hoaks>
Ong, Jonathan Corpus and Ross Tapsell, ‘Demystifying Disinformation Shadow Economies: Fake News Work Models in Indonesia and the Philippines’ (2022) 32(3) Asian Journal of Communication 251
Rasidi, Pradipa P, ‘Of Play and Good Men: The Moral Economy of Political Buzzing in Indonesia (Forthcoming)’ [2021] Digital Technologies and Democracy in Southeast Asia
Sastramidjaja, Yatun, ‘Beating the Buzzers’, Inside Indonesia (2021)
Sinpeng, Aim, Ross Tapsell and ISEAS-Yusof Ishak Institute (eds), From Grassroots Activism to Disinformation: Social Media in Southeast Asia (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2021)
Sugiono, Shiddiq, ‘Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media’ (2020) 4(1) Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi 47
Camil, Rinaldi and Klara Esti, ‘Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri Dan Pengaruh Buzzer Di Indonesia’
Digital Industry Group Inc, ‘Disinformation Code’, digi.org.au (2023) <https://digi.org.au/disinformation-code/>
Rowland MP, The Hon Michelle, ‘New ACMA Powers to Combat Harmful Online Misinformation and Disinformation’ (2023) <https://minister.infrastructure.gov.au/rowland/media-release/new-acma-powers-combat-harmful-online-misinformation-and-disinformation>
[1] Aim Sinpeng, Ross Tapsell dan ISEAS-Yusof Ishak Institute (eds), From Grassroots Activism to Disinformation: Social Media in Southeast Asia (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2021) (‘From Grassroots Activism to Disinformation’).
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Pradipa P Rasidi, ‘Of Play and Good Men: The Moral Economy of Political Buzzing in Indonesia (Forthcoming)’ [2021] Digital Technologies and Democracy in Southeast Asia.
[5] Ibid.
[6] Kate Lamb, ‘“I Felt Disgusted”: Inside Indonesia’s Fake Twitter Account Factories’, The Guardian (2018).
[7] Ika Idris, Laeeq Khan and Nuurrianti Jalli, ‘Indonesia’s Misinformation Army Ready for War in 2023’, tempo.co (2023).
[8] Rasidi (n 4).
[9] Ibid.
[10] Ibid.
[11] Shiddiq Sugiono, ‘Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media’ (2020) 4(1) Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi 47 (‘Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia’).
[12] Rinaldi Camil dan Klara Esti, ‘Di Balik Fenomena Buzzer: Memahami Lanskap Industri dan Pengaruh Buzzer di Indonesia’.
[13] Lihat misalnya Jonathan Corpus Ong dan Ross Tapsell, ‘Demystifying Disinformation Shadow Economies: Fake News Work Models in Indonesia and the Philippines’ (2022) 32(3) Asian Journal of Communication 251 (‘Demystifying Disinformation Shadow Economies’).
[14] Sebastian Gallander, ‘Why Volunteering Is the Pulse of Democracy’, TwentyThirty. (2018).
[15] Rasidi (n 4).
[16] See e.g. Yatun Sastramidjaja, ‘Beating the Buzzers’, Inside Indonesia (2021).
[17] Ika Ningtyas, ‘Menguatnya Kontrol Negara Di Ruang Digital Dengan Dalih Memerangi Hoaks’, Remotivi (online, 2023) <https://www.remotivi.or.id/amatan/800/menguatnya-kontrol-negara-di-ruang-digital-dengan-dalih-memerangi-hoaks>.
[18] Digital Industry Group Inc, Australian Code of Practice on Disinformation and Misinformation (2022) <https://digi.org.au/disinformation-code/>.
[19] European Commission, ‘The 2022 Code of Practice on Disinformation’, European Commission (online, 2022) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>.
[20] Digital Industry Group Inc, ‘Disinformation Code’, digi.org.au (2023) <https://digi.org.au/disinformation-code/>.
[21] Lamb (n 6).
[22] Australian Communications and Media Authority, Report to Government on the Adequacy of Digital Platforms’ Disinformation and News Quality Measures (2021) <https://www.acma.gov.au/report-government-adequacy-digital-platforms-disinformation-and-news-quality-measures>.
[23] The Hon Michelle Rowland MP, ‘New ACMA Powers to Combat Harmful Online Misinformation and Disinformation’ (2023) <https://minister.infrastructure.gov.au/rowland/media-release/new-acma-powers-combat-harmful-online-misinformation-and-disinformation>.